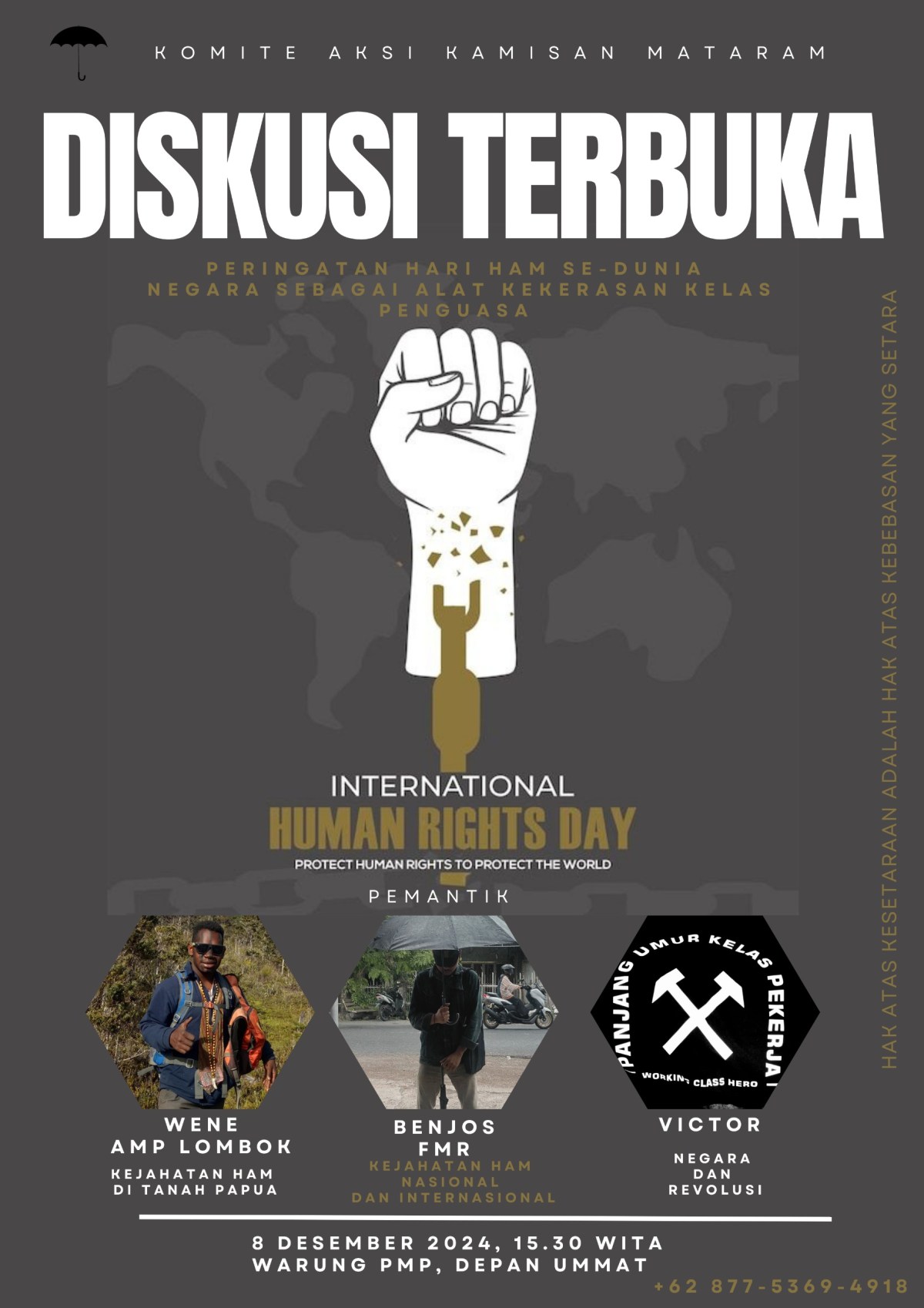“Kita perlu berjuang secara sadar untuk menghancurkan alat kekerasan yang paling konservatif ini; marilah kita sama-sama mendalami karakter negara borjuis ini. Ketimbang saling pandang-memandangi dengan penuh kecurigaan dan rasa ingin tahu yang penuh kebimbangan; marilah kita saling-mengulurkan tangan secara tulus, penuh persahabatan, dan dengan pikiran yang terbuka untuk mendiskusikan pertanyaan mengenai hak asasi yang tragis dan negara yang sadis ini. Marilah kita singkirkan tentang keyakinan tanpa akal sehat terhadap asas-asas pemerintahan yang baik, dan janganlah ada sebutan lain yang terdengar kecuali seruan solidaritas dari angkatan muda dan rakyat pekerja yang baik; para penyokong yang berpendirian tegas, jujur, dan tanpa pamrih terhadap hak-hak manusia yang tertindas dan terhisap.” (Kaum Bolshevik)
Umat manusia berada di persimpangan sejarah yang penuh ironi. Di satu sisi—pencapaian ilmu-pengetahuan, teknik dan industri menunjukkan jalan ke depan yang gemilang, berisi kemakmuran, kesejahteraan sosial, dan kemajuan budaya yang tiada tara. Di lain sisi—eksistensi semua spesies yang ada terancam oleh pengrusakan planet atas nama pengejaran keuntungan secara membabi-buta. Dalam “Kekerasan dan Kapitalisme; Pendekatan Baru dalam Melihat HAM”, Jamil Salmi menulis: ‘akumulasi modal berbanding lurus dengan akumulasi kekerasan: perbudakan, rasisme, perang, kelaparan, dan segala kejahatan yang tak terungkap’. Salmi membagi kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi empat jenis kekerasan: (1) kekerasan langsung—penyerangan fisik atau psikologis tanpa prantara (2) kekerasan represif—pembatasan terhadap hak sipil, politik, dan sosial; (3) kekerasan alienatif—pencabutan hak individu dalam perkembangan emosional dan intelektual; dan (4) kekerasan tak langsung—tidak melibatkan hubungan langsung korban dengan pelaku namun sangat membahayakan korbannya. Aneka kekerasan ini dapat, dan hanya bisa, dilakukan secara sempurna oleh negara. Negara bukan akar kekerasan tapi aktor utama yang sangat profesional dalam melancarkan kekerasan yang beraneka rupa itu. Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin telah menjelaskan kalau aneka bentuk kekerasan itu berlangsung di seputar persoalan negara yang berdiri di atas pertentangan kelas-kelas sosial yang ada. Negara adalah badan orang-orang bersenjata, seperti polisi dan tentara reguler, dengan konstitusi dan hukum, penjara dan peradilan, dan beragam institusi kekerasan lainnya, yang terbentuk ketika masyarakat terbagi menjadi tuan-budak dan budak, tuan-tanah dan hamba, borjuis dan proletar. Dalam melindungi hak-hak istimewa kelas penguasa, negara memonopoli segala sarana kekerasan dengan dalih perdamaian, ketertiban, dan kemananan. Dalam ‘Pengantar’ untuk “Negara dan Revolusi”, Alan Woods menjelaskan:
“Asal-usul negara berakar pada hubungan produksi dan bukan pada kualitas pribadi. Pada masyarakat manusia awal, otoritas kepala suku bergantung pada keberaniannya dalam pertempuran, otoritas para tetua suku bergantung pada kebijaksanaan mereka, dan lain-lain. Namun saat ini negara dijalankan oleh pasukan individu yang tidak dikenal, birokrat dan fungsionaris anonim, yang otoritasnya diberikan kepada mereka melalui jabatan yang mereka pegang dan gelar yang diberikan kepada mereka. Mesin negara adalah mnster yang tidak manusiawi yang, meskipun secara teoritis melayani masyarakat, pada kenyataannya berdiri di atasnya sebagai tuan dan majikan masyarakat…. Setiap bentuk kekuasaan negara melambangkan dominasi satu kelas atas kelas lainnya. Bahkan dalam bentuk yang paling demokratis, hal ini melambangkan kediktatoran satu kelas—kelas penguasa—kelas yang memiliki dan mengendalikan alat produksi. Merangkum analisis historisnya tentang negara, Friedrich Engels mengatakan: ‘…Negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini telah terjerat dalam kontradiksi yang tak-terpecahkan dalam dirinya sendiri, bahwa masyarakat telah terbagi dalam antagonisme kelas yang tak-terdamaikan. Namun, agar antagonisme ini, kelas-kelas dengan kepentingan ekonomi yang saling-berlawanan, tidak menghabiskan diri mereka sendiri dan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka diperlukan suatu kekuatan, yang tampaknya berdiri di atas masyarakat, yang akan meredakan pertentangan dan menjaganya dalam batas=batas ‘ketertiban’; dan kekuatan ini, yang muncul dari masyarakat tetapi menempatkan dirinya di atasnya, dan semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara.”
Negara adalah institusi kekerasan yang terorganisir dan bertugas memaksakan kepentingan kelas penguasa terhadap kelas-kelas yang tertindas. Kekuatan ini berasal dari masa lalu yang jauh; di mana dalam bentuk-bentuk masyarakat kelas awal, negara menampilkan kekerasannya seperti monster pembunuh yang berdarah dingin—ganas dan sadis: melahap daya kerja para pekerja tradisional dalam jumlah yang meraksasa, mencabik-cabik perjuangan massa dan merampas hak-hak asasi mereka. Dalam pertentangan kelas-kelas sosial yang ada, negara tidak pernah muncul sebagai penengah yang menetralkan pertikaian antara kelas dan mendamaikan kepentingan-kepentingan kelas yang bertentangan secara antagonis. Kehadiran negara justru menjadi instrumen penindasan untuk mempertahankan perbudakan dan penghisapan kelas minoritas atas kelas mayoritas; jika Republik Romawi berdiri sebagai instrumen untuk menindas kaum budak dan negara feodal menjadi instrumen untuk menindas kaum tani-hamba, maka negara modern merupakan instrumen untuk mengeksploitasi kaum buruh-upahan. Melalui “Manifesto Komunis”, Marx dan Engels menjelaskan bahwa negara modern ‘hanyalah sebuah komite untuk mengelola urusan bersama seluruh kelas borjuis’. Di setiap negara borjuis, birokrasi memiliki kepentingan yang kuat untuk mengatur perjuangan kelas dan menjaganya untuk tetap berada pada batas-batas yang bisa diterima. Dalam periode yang relatif damai, kelas penguasa menjalankan kendali atas negara dengan kekuasaan hegemoni yang kuat. Namun pada periode-periode tertentu—krisis, perang dan revolusi; perjuangan kelas bertambah intens dan tidak dapat lagi dijinakan melalui hegemoni borjuasi. Inilah saatnya pertanyaan kekuasaan mengemuka: apakah kelas revolusioner akan berhasil menghancurkan negara lama dan menggantinya dengan negara baru, atau kelas penguasa meluluhlantahkan perjuangan revolusioner massa dengan memaksakan kediktatoran (kekerasan negara dalam bentuk yang tidak-terselubung, sebagai antipode dari kekerasan negara dalam selubung demokratis)?
Namun ketika kelas-kelas yang bertentangan telah bertempur tanpa hasil yang jelas dan ketika kelas-kelas yang bertarung mencapai semacam keadaaan kesimpangan yang tidak-stabil, negara yang sebelumnya nampak terselubung berdiri di atas masyarakat terdorong dengan terang-terangan ke puncak masyarakat dan memperoleh tingkat kemandirian yang relatif besar. Di zaman kuno ini mengambil bentuk Caesarisme dan di dunia modern ini dikenal sebagai Bonapartisme. Dalam sejarah Indonesia modern, kekuasaan Soeharto dapat diasosiasikan dengan Bonapartisme. Di tengah kepengecutan borjuasi nasional (Soekarnois) dan kelemahan bawaan dari Kepemimpinan PKI (Stalinis), perjuangan revolusioner massa diseret ke jalan buntu. Di akhir 1950-an dan awal 1960-an, pendulum politik berayun tajam ke kiri dan massa menjadi kekuatan utama yang mendorong revolusi. Massa siap untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno dan menghancurkan negara borjuis, namun Kepemimpinan PKI (Stalinis) berkolaborasi-kelas dan sepenuhnya mendukung Pemerintahan Soekarno. Saat aksi-aksi revolusioner berusaha bergerak menerobos batas-batas kepemilikan borjuasi, para pemimpin Stalinis justru mendapati dirinya dalam kengerian yang luar biasa. Tanpa jenderal yang bersungguh-sungguh dan tegas untuk merebut kekuasaan, maka perwira-perwira buruh dan tani seketika kehilangan arah. Tidak ada slogan atau panduan apa-apa. Aksi-aksi massa yang melibatkan berjuta-juta proletar dan semi-proletar dibiarkan berlarut-larut sampai kehilangan tenaga. Dan pada momen kelelahan tiba, pendulum politik berayun keras ke kanan; yang ditandai dengan bangkitnya elemen yang paling konservatif dalam tubuh militer yang mendapat dukungan imperialisme untuk membasmi massa. Periode kebangkitan pada akhirnya beralih menjadi kemunduran yang panjang, begitu menyakitkan dan berdarah-darah. Inilah yang dibuka dengan malapetaka 1965. Dalam “Musim Menjaggal”, Geofrey B. Robinson, merekam pembantaian massa yang meraksasa: ‘sepanjang September-November 1965, mula bukanya pembunuhan massal dilangsungkan di Aceh: hasilnya 10.000 warga binasa. Lalu awal November beranjak ke Medan: akibatnya 40.000 buruh perkebunan dan pertanian merenggang nyawa. Kemudian penjagalan memasuki Jawa Tengah pada minggu ketiga bulan Oktober: 140.000 meninggal dunia. Dan memasuki Desember pembantaian dilanjutkan ke Jawa Timur, Bali, dan NTT: masing-masing jumlah korban yang dibunuh di setiap daerah mencapai 180.000, 80.000, dan 60.000 jiwa’.
Pembunuhan massal itu dilakukan Rezim Bonapartisme Soeharto untuk menyingkirkan semua anasir yang bagi dirinya dan sekutu-sekutunya dapat menghambat proyek-proyek pembangunan kapitalisme-imperialisme. Setelah berhasil memastikan kemenangnya dari segala yang berbau komunis, maka Soeharto kemudian menamkan pembangunannya sesuai pesanan Bank Dunia. Dalam Model Pembangunan Versi Bank Dunia (1994), Ali Sugihardjanto membagi upaya membangun yang dilakukan Orba ke dalam tiga fase. Periode pertama (1967-1973): pemerintah memiliki ciri khusus yaitu politik pintu terbuka yang mengusahakan berbagai insentif untuk menarik penanaman modal asing, antara lain melalui usaha-usaha pembuatan infrastruktur, UU PMA yang memikat dengan membuat restriksi industri yang sangat sedikit. Periode kedua (1973-1983): pemerintah mengerahkan politik industrinya pada kegiatan industri impor substitution melalui berbagai proteksi bagi kepentingan pasar dalam negeri, yang bertujuan menaikan kandungan lokal dalam hasil produksi. Di bidang ekspor pemerintah melarang ekspor beberapa bahan mentah dalam bentuk belum diolah, yang bertujuan membangun industri barang-barang ekspor. Periode ketiga (1983-1992): pemerintah telah memberi arah baru menuju industri berorientasi ekspor ditandai oleh pembukaan hampir semua sektor industri manufaktur bagi investasi asing, dengan mengandalkan daya tarik tenaga kerja yang murah.
Pelaksanaan cara membangun sesuai dengan kompetisi pasar di tingkatan dunia. Fondasi tatanan ekonomi Internasional saat Soeharto mengambil-alih kekuasaan berada di atas kendali Amerika Serikat: benteng reaksi imperialis yang sedang mengembangkan sistem Bretton Woods dan Marshall Plan—kedua proyek dimaksudkan untuk menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan pasar dunia yang berada di bawah monopolinya. Makanya sesaat setelah berkuasa, kelompok kapitalis yang mendapat perlindungan Bonapartisme melaksanakan pertemuan kilat di Jenewa dan mengeluarkan aturan pro-ekonomi liberal yang sedang digalakan Amerika: UU No. 9 Tahun 1966—melalui peraturan inilah Indonesia dituntut bergabung dalam International Monetary Fund (IMF). Dengan menjadi anggota IMF, Rezim Orba semakin mengemis-ngemis modal asing hingga menyetutujui kesepakatan gila: menggadaikan kekayaan bangsa atas nama proyek-proyek pembangunan dan investasi. Dalam sebuah karyanya Jeffrey A. Winters pernah menjelaskan begini: ‘konsersium yang dipimpin oleh Amerika membuat tanah Indonesia telah dikotak-kotakkan untuk dibagi-bagi kepada mereka yang ada dalam ruangan. Mereka membaginya ke dalam lima seksi, yakni: pertambangan, jasa-jasa, industri ringan, perbankan dan keuangan. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang berkuasa di dunia, di antaranya: David Rockefeller, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, The International Paper Coeporation, US Steel dan Henry Kissinger. Indonesia pun akhirnya, seperti biasa, efeknya sampai sekarang: menjual buruh murah, pajak rendah dan kekayaan alam sebagai tukar-guling utang, hingga tidak ada ketahanan energi dan pangan’.
Di bawah Rezim Orba, pembangunan diangkat sebagai ideologi yang berdiri di atas kepentingan kapitalisme-imperialisme. Pembangunanisme memoles kekuasaan negara hingga menampakan wajahnya persis apa-yang-dimaksud Gramsci sebagai ‘negara integral’: hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi. Negara yang integralistik ini bukan hanya memiliki perangkat lunak (pendidikan, kebudayaan, agama, media, penerbitan, hingga pranata keluarga), tapi juga perangkat keras (TNI-Polri, pengadilan, birokrasi, bahkan segala administrasi). Dengan mempergunakan kedua perangkat kekuasaannya maka ideologi hegemonik tidak saja bekerja di atas persetujuan malainkan pula paksaan yang mendominasi. Kombinasi antara hegemoni dan dominasi inilah yang mengakibatkan rakyat mudah disulap jadi spesises yang patut dipenjarakan, bahkan sampai tak segan-segan dieksekusi mati. Setelah memastikan kehacuran ideologi dan gerakan komunisme, selanjutnya Orba memuluskan kepentingan kapitalisme internasional dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA). Berpatokan pada aturan tersebut maka dibuatlah Kontrak Karya yang memmberikan kesempatan kepada perusahaan Exxon Mobil dan PT Freeport asal Amerika untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
Pada 1968, Exxon Mobil diijinkan masuk ke Aceh pada 1968. Di tahun 1971 perusahaan itu menemukaan ladang gas alam di Lapangan Arun, Aceh Utara. Penemuan ini direspon oleh Orba dengan mengadakan perjanjian pembagian keuntungan: pemerintahan Soeharto menerima 70 persen keuntungan danExxon Mobil sendiri menerima 30 persen. Namun Aceh sendiri hanyamenerima manfaat yang minimum: Pemerintah Daerah dan masyarakat setempathanya mendapat 5 persen keuntungan yang disalurkan dari Jakartake Aceh. Inilah sebabnya rakyat aceh merasa telah diperlakukan tidak adil oleh penguasa dan pengusaha. Hanya kedua penindas itu begitu lincah.Dalam kontrak awal, Exxon memberikan saham yang tak diperinci besarnya dalam cabang perusahaannya di Indonesia kepada Soeharto sekaligus mempekerjakan anggota TNI-Polri sebagai personil keamanan. Sejak saat itulah penduduk di sana bukan hanya dimisikinkan dan sering mendapatkan kekerasan. Tetapi juga ikut dicerabutkan dari kultur keagamaannya. Dalam Aceh Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, KontraS menceritakannya begitu rupa:
“Kekayaan alam Acehterus dikuras oleh Pusat dengan sistem kebijakan yangsentralistik dan hanya menjadikan Aceh sebagai ‘sapi perahan’.Rakyat Aceh tetap miskin. Apalagi label ‘Daerah Istimewa’ bagidaerah Aceh telah dikebiri oleh pemerintah Orde Baru, ditambahrakyat Aceh hanya bisa terkesima melihat daerah dijarah secaraeksplosif oleh Pusat, namun nasib tiga juta rakyatnya saat ituterus menerus mengalami keterpurukan…. Sejak itu pemerintah Indonesia memberi Mobil Oil hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan menambang gas alam di area sekitar Arun.…Rakyat Acehhanya bisa melihat dengan tetesan airmata, saat kekayaan alamtanah leluhurnya dikuras habis-habisan oleh tangan-tangan asingyang membawa mandat pusat. Bukan hanya itu, keangkuhanyang ditimbulkan dari keberadaan kawasan industri di AcehUtara telah pula melahirkan dan menyebarkan virus dekadensimoral bagi anak-anak generasi penerus di Aceh. Lokasi-lokasipelacuran gelap, diskotik, dan pub bertebaran dari Aceh Timur. utara hingga ke Banda Aceh. Bagi masyarakat modern hal itudisadari sebagai dampak dari berputarnya roda industri. Bagimasyarakat Aceh hali ini dianggap sebagai penghancuran syariat Islam. Nilai-nilai agama semakin terpinggirkan dan seakan takpopuler lagi untuk mendapat tempat di tengah-tengah gemuruhmesin industri yang saat itu mulai berputar di Lhokseumawe, Aceh Utara.”
Apa yang dialami rakyat Aceh serupa dengan yang dirasakan bangsa Papua. Lewat KK yang berpatokan pada UU PMA, Orba menjual kekayaan alamnya: emas hingga tembaga. Korban darinya adalah penduduk kecil seperti suku Amungme dan suku-suku lain. Mula-mula kawanan serdadu dikirim untuk memaksa mereka tunduk terhadap Pemerintah Indonesia melalui manipulasi Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969. Kala itu Soeharto berhasil mendapatkan persetujuan orang-orang Papua dengan mengerahkan kekuatan militer dalam memobilisir massa melalui bujuk-rayu juga ancaman kekerasan. Skemanya dimulai dengan penujukan Perwira Intelijen Ali Murtopo untuk merancang Operasi Khusus (Opsus). Tujuannya agar bangsa Papua menerima pengintegrasian daerahnya menjadi bagian wilayah kekuasaan negara. Demi menyukseskan misi ini maka Ali memadukan cara persuasif dan intimidatif—berkompromi, menyuap, sampai menakut-nakuti siapa saja yang menolak keinginan penguasa. Dalam menundukan orang-orang Papua, sejarahwan Australia—Edward Elson, membeberkan operator lapangannya ternyata dipimpin oleh Brigjen Sarwo Edhie. Panglima Kodam Cendrawasih ini diberi tugas najis: mempreteli kehendak orang-orang Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Makanya mulut kepala-kepala suku dan para wakil rakyat ditutupi dengan uang. Sedangkan bagi penduduk yang mencoba beraspirasi akan diterjang dengan perlakuan yang sewenang-wenang.Walhasil, menjelang sidang Pepera Agustus 1969 Angkatan Darat (AD) memastikan kemenangan Soeharto atas bangsa Papua: 1025 orang yang pro-integrasi dihadirkan untuk menentukan pendapat dalam mendukung keputusan penguasa Orba. Mereka dipaksa mengeluarkan pendapanya di bawah todongan senjata. Lewat artikelnya diHistoria, Martin Sitompul mengatakan: ‘Opsus Ali Murtopo berjalan mulus. Soeharto bernafas lega karena kemenangan Pepera ada dalam genggaman. Freeport dengan leluasan merambah kekayaan alam Papua’.
Dalam negara kapitalis, baik yang Bonapartis maupun demokratis, kekayaan-kekayaan alam tidak pernah diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan kerakusan kelas borjuis. Permulaan 1970-an penderitaan massa-rakyat meliputi: penurunan persediaan pangan nasional, petani-petani semakin miskin karena hasil panennya tidak dibeli oleh Bulog, peningkatan harga komoditi secara umum, pencabutan program subsidi BBM sekaligus naiknya harga BBM serta tarif listrik, dan terutama banyaknya buruh yang di-PHK. Akumulasi dari semua derita inilah yang melahirkan Peristiwa Malari 1974: rakyat miskin dan tertindas itu bergabung bersama ribuan mahasiswa dan siswa. Mereka bersepakat menerbitkan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Ketidakpuasan terhadap birokrasi yang membesarkan koruptor dan menguntungkan pemodal telah mengakibatkan masyarakat murka. Mereka bersepakat turun ke jalan dengan memancang tiga tuntutan: (1) bubarkan lembaga asisten pribadi presiden (Aspri); (2) turunkan harga kebutuhan pokok; (3) ganyang korupsi dalam tubuh birokrasi. Ketiga tuntutan itu terbingkai dalam kesadaran bersama: tolak derasnya investasi asing—terutama pinjaman modal dari Jepang—yang membanjiri Indonesia. Makanya parlemen jalanan digelar bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kekuei Tanaka di Jakarta. Kehadirannya disambut sikap dan aksi berlawan dari elemen masyarakat sipil. Soalnya kunjungannya berisi kepentingan modal asing.
Hanya suara-suara protes tersebut mudah saja dipentalkan Orba dengan pengerahan serdadu bersenjata.Makanya dalam Malari, Soeharto bereaksi amat durjana. Banyak sekali mahasiswa dan pimpinan gerakan yang ditangkap, dijadikan sebagai tahanan rumah, hingga diadili untuk dimasukan ke sel tahanan. Bahkan lima koran kritis yang membantu menyatukan keresahan masyarakat dalam aksi-aksi protes dibredel: “Indonesia Raya”, “Abadi, Nusantara”, “Harian Kami”, “Mahasiswa Indonesia”, dan “Pedoman”. Sementara korban kekerasan terbanyak datangnya dari masyarakat sipil: 11 nyawa melayang dan 300 orang penuh luka di sekujur badan. Tetapi untuk mennggulangi krisis yang berlangsung, Orba tidak hanya melancarkan represi melainkan pula berusaha mencari daerah akumulasi baru. Kala itu Timor Timur dianggap dipandang sebagai daerah yang mampu bemberikannya kutipan laba. Maka invans dilakukan mulai tahun 1974/75.Tujuannya tidak hanya untuk memaksa penduduk mengintegrasikan diri ke dalam Indonesia, tapi terutama supaya bisa mematikan gerakan rakyat dan menguasai kekayaan alam yang ada di sana. Mula-mula mendapati informasi bahwa terdapat limpahan kandungan minyak dan gas di bawah Laut Timurdari kontraktor migas asal Australia: Woodside. Kontraktor itu menemukan ladang Gas Greater Sunrise di Timur-Portugis (Timor-Leste). Lokasinya berada di lepas laut Timor—150 km Tenggara Timur-Portugis dan 450 km Barat Laut Darwin. Di sana terkandung potensi cadangan 2,13 tcf dan potensi omzet hingga 50 miliar dollar AS. Setelah penemuan inilah operasi-operasi militer dilakukan secara sistematis: Operasi Komodo 1974 untuk menciptakan kekacauan, lalu 7 Desember 1975 dilakukanlah Operasi Seroja yang sampai 17 Juli 1976 telah berhasil mengerahkan 30.000 pasukan bersenjata Indonesia untuk menduduki Timor sekaligus menumpas orang-orang yang terlibat keributan. Setelah kekacauan yang sengaja dibikin berhasil dihentikan sendiri oleh penciptanya, maka pada 1975 Timor-Leste dipaksa berintegrasi ke dalam Indonesia menjadi Timor-Timur. Pendudukan ini disponsori oleh banyak sekali negara kapitalis maju: sepanjang 1975-1978 TNI-Polri mendapatkan bantuan persenjataan canggih dari AS, Australia, Belanda, Korsel, Taiwan, dan Jerman Barat. Dalam sebuah artikel menjelaskan bahwa pendudukan militer Orba bukan sekedar mencabut nyawa rakyat Tim-Tim, tapi juga membuatnya melarat:
“Dalam tiga tahun pertama masa pendudukan jumlah kematian mencapai sepertiga dari persentase jumlah penduduk keseluruhan: 1974 warga yang terbunuh sebanyak 688.771 jiwa, lalu pada Oktober 1978 menjadi 329.271 jiwa. Ini merupakan angka korban tewas tertinggi dalam sejarah pembantaian pasca Perang Dunia II. Sebagian besar kematian terjadi karena pembunuhan yang disengaja dan penghilangan paksa oleh TNI-Polri. Tujuan tindak kejahatan kemanusiaan itu begitu dangkal: sebagai bentuk kontrol agar penduduk sipil tidak memberi dukungan kepada Fretilin. Selain digencarkan pembunahan dan penghilangan, ewasnya rakyat Timur Leste juga disebabkan penyakit dan kelaparan akibat pendudukan. Invansi soalnya telah menghalangi akses kesehatan dan menghancurkan sumber-sumber makanan. Keadaan ini diperparah lagi dengan tiadanya sarana kehidupan yang layak setelah pemindahan penduduk secara paksa ke pemukiman baru serta pembatasan kebebasan bergerak. Itulah mengapa berbagai pelanggaran HAM merebak; mulai dari budaya kekerasan yang dilestarikan dengan menciptakan suasana saling memata-matai di antara warga Timor-Leste, represi sistematis terhadap kaum perempuan, pemaksaan sterilisasi (KB) terhadap ibu-ibu rumah tangga, sampai perekrutan anak-anaknya menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi) militer.”
Dorongan mengeruk laba dalam sistem kapitalisme bukan hanya membuat negara melakukan pendudukan, tapi juga telah mengharuskan dibunuhnya orang-orang yang dianggap dapat menggerogoti akumulasi keuntungan. Makanya sepanjang 1982-1985, Soeharto mengerahkan ABRI untuk menembak semua yang menggagu proses produksi perusahaan. Peristiwa ini abadi sebagai Penembakan Misterius (Petrus). Di dalamnya terdiri dari tindakan perampasaan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Pada 1982, Yogyakarta jadi tempat pertama yang mengalami keempat bentuk kejahatan negara barusan. Algojonya berasal dari kawanan ABRI. Tugasnya sederhana: menembak dan menghilangkan paksa orang-orang yang dituduh merisaukan pengusaha. Kala itu bos-bos besar memang suka didatangi dengan tujuan meminta uang yang tidak seberapa. Maka bos yang rakus bukan sekedar melabeli mereka sebagai sampah masyarakat (gali dan sebagainya), melainkan pula melaporkannya terhadap aparat-aparat represif negara. Sebenarnya orang-orang itu nekad menagih uang pada perusahaan karena masalah ekonomi memaksanya berbuat demikian. Sampai tahun 80-an terdapat tiga ketimpangan pembangunan: (1) kesenjangan industri dan pembangunan; (2) kesenjangan antara desa dan kota; dan (3) kesenjangan kaya dan miskin. Data BPS 1981 mencatat: penduduk miskin Indonesia mencapai 42,3 juta jiwa. Warga-warga ini bergelut dengan permasalahan hidup yang begitu rupa: ada yang sudah bekerja tapi gaji sedikit, hingga paling banyak adalah yang menganggur sana-sini.Kedua kelompok tersebut bernasib serupa: dibelenggu dalam kemiskinan yang menyeringai. Sayangnya kelas borjuasi tak mau sedikitpun berempati. Di Yogyakarta, justru kaum miskin dan tertindas dilaporkannya ke ABRI. Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta Letkol CZI M. Hasby dan Pangdam VII Diponogoro Mayjen TNI Soegiarto, kontan bersepakat mengeluarkan keputusan perang terhadap para gali.Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat dari Komnas HAM menjelaskan kejahatan yang berlangsung itu begini:
“Dengan resep tembak langsung, para gali di Yogyakarta berjatuhan satui persatu mati. Sisanya kocar-kacir…. Selain pembunuhan dan eksekusi di luar proses pengadilan sejumlah preman di Yogyakarta juga mengalami proses penangkapan secara-semena-mena…. Banyak di antara korban mati maupun survivor yang mengalami penyiksaan. Di antara korban mati bisa dikenali adanya penyiksaan ini dari tanda-tanda yang terdapat pada jenasah mereka. Perang terhadap para gali di Yogyakarta juga menggunakan cara perampasan kemerdekaan. Secara umum, korban biasanya dibawa oleh lebih dari 1 orang anggota ABRI yang kadang mengunakan seragam loreng tanpa adanya surat penangkapan. Sebagian lagi dijemput oleh orang bertopeng atau orang yang tak dikenali, baik oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Sebagian dari korban ditemukan masyarakat dalam bentuk sebagai jenasah. Sebagian dari orang-orang yang dijemput pada akhirnya menjadi korban. penghilangan orang secara paksa di mana orang yang menjadi target dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban, dijemput atau dijebak oleh teman korban, diminta memenuhi panggilan polisi untuk datang ke kantor polisi….”
Rezim Bonapartis benar-benar tidak-stabil. Kekacauan meledak-ledak. Kabinet mudah sekali dirombak. Tetapi para pejabat semakin buncit dan pengusaha bertambah kaya-makmur. Sementara rakyat pekerja terus-menerus dieksploitasi dan mendapat penindasan yang begitu kompleks. Laki-laki dan perempuan miskin diperlakukan secara banal. Mereka dijagal. Komnas HAM merekam; pada minggu pertama Juli 1983 ada 17 mayat residivis ditemukan di Kabupaten Tegal. Sampai pertengahan Juli 1983, ditemukan lagi 20 mayat wargadi seputar Solo, bahkan 7 di antaranya tewas dalam waktu 5 hari. Total hasil pelaksanaan operasi militer pada 1982-1983 di Daerah Kowil 95 Solo, sekitar 35 tertuduh penjahat mati tertembak. Lalu sejak 10-15/16 Juli 1983, tercatat 7 orang tewas: 5 meninggal akibat terkena tembakan dan 2 lainnya binasa karena lehernya dijerat dan dicekik. Orba memang sudah biasa mengacam dan melenyapkan rakyatnya dengan diawali stigma-stigma jahat. Massa-rakyat bukan sekadar dibinasakan dengan tuduhan anggota atau simpatisan PKI tapi label penjahat. Berbekal anggapan sinting itulah Petrus yang terjadi antara 1982-1985 mampu membuat ribuan manusia tak berdosa mendadak dilaknat. Penduduk di berbagai wilayah Indonesia, terutama Jawa—diubah jadi mayat dengan luka tembak atau jempol terikat. Jenazah-jenazahnyaberserakan seperti rerompahan daun yang bertebaran di mana-mana: ditemukan di berbagai lokasi, mulai dariselokan, sawah, sungai, jurang, tepi pantai, hingga jalan raya. Total korban pembunuhan oleh negara tercatat mencapai angka 9.000 jiwa. Keterlibatan negara yang terlalu dalam untuk mengatur kelancaran sirkulasi barang dan jasa demi kemantapan akumulasi kapital di tangan para pemodal mengakibatkan rakyat-rakyat kecil jadi sasaran kekerasan dan pembunuhannya. Dalam perspektif marxis negara memang diperintah oleh pemerintah namun kelas kapitalislah yang mengaturnya. Karena negara yang menyemai tatanan kapitalisme hanya berfungsi untuk: (1) legitimasi: upaya menciptakan konsensus bagi warga negara menyangkut kebenaran dasar ekonomi dan integritas moral masyarakat kapitalis, sehingga negara begitu aktif mendorong dukungan ke arah status quo politik dan ekonomi; (2) penindasan: tindakan yang dilakukan apabila legitimasi gagal dan hegemoninya semakin berkurang. Maka represifitas merupakan cara ampuh dalam mencegah massa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negara sekaligus membahayakan kelangsungan kapitalisme; dan (3) akumulasi: usaha untuk membuat dan menetapkan kebijakan yang bisa memuluskan kelas kapitalis dalam mengumpulkan modal. Caranya seperti menciptakan undang-undang peringanan beban pajak bagi pemodal maupun menggeser beban pajak tersebut pada rakyat pekerja dan membuat pelbagai kebijakan-kebijakan naïf untuk mendorong pemerasannya.
Bahkan fungsi legitimasi yang diancarkan Soeharto adalah dengan memanfaatkan Pancasila. Pancasila dalam pemerintahan Orba tidak sebatas jadi dasar negara, tapi juga asas tunggal segala. Dengan mengasastunggalkannya maka kelas penguasa hendak mendikte semua elemen gerakan baik organisasi mahasiswa, sosial, politik, maupun agama. Hanya ambisi mengonsentrasikan kekuasaan ini kemudian membawa petaka pada 1984: Peristiwa Tanjung Priok di Jakarta Utara. Mula-mula di bulan Juni, negara menuduh para mubaligh menyampaikan ceramah-ceramah radikal saat melaksanakan ibadah tarawihnya:bukan saja masalah korupsi dan modal asing, melainkan pula pelarangan penggunaan jilbab danpemaksaan keluarga berencana (KB) dan sebagainya. Bahkan di dinding-dinding Mushola As Sa’adah dipasang pamflet-pamflet bertulisan bahasa Arab yang intinya menentang kebijaksanaan pemerintahan. Mereka tidak tahan melihat pelajar sekolahan dipakaikan pakaian seragam sekaligus yang sisiwi dilarang memakai jilbab. Pakaian seragam sangat menyulitkan kehidupan anak-anak sekolah bukan sekedar untuk melaksanakan tradisi kegamaan dalam berjilbab, tapi juga meminggirkannya dari akses transportasi-angkutan. Lihatlah bagaimana di kota-kota besar: murid-murid SD hingga SMA menjadi pasar sosial bagi industri pertransportasian. Dengan atribut pakaian seragam maka pelajar-pelajar itu tarif angkutannya sudah ditentukan terlebih dahulu: tarifnya tiga kali lebih rendah daripada penumpang pada umumnya. Walhasil, sopir-sopir bus kota lebih banyak menjauhinya karena tidak terlalu menguntungkan. Sehingga pemakaian pakaian seragam sebetulnya lebih memudahkan pengindentifikasian terhadap penumpang-penumpang yang berbayaran rendah. Tetapi dalam industri tekstil penyeragaman pakaian anak sekolahan begitu menggiurkan. Keadaan inilah yang membuat industri pertekstilan berbondong-bondong memegang monopoli produksi pakaian. Bahkan siapa yang memproduksi seragam sedari awal ditentukan langsung oleh penguasa yang menjadi konco-konconya.
Kebijakan penyeragaman pakaian itu persis dengan Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan hasil tekanan dari lembaga-lembaga internasional, yang mendesak Orba melakukan kontrol terhadap alat reproduksi: bertujuan mengendalikan pertumbuhan dan pembiakan tubuh dalam arti nimerik—jumlah penduduk suatu negara. Baginya penduduk yang tidak terkontrol dapat merebut sumber daya ekonomi politik: artinya berpotensi merusak pendapatan penguasa. Apalagi pada 1983, negara baru saja mengeluarkan Pakjun 1983. Kebijakan ini memberi keuntungan besar bagi segenap kapitalis-swasta. Hidup dalam lingkungan yang diselimuti kenyataan-kenyataan seperti ini mendorong masyarakat Tandjung Priok memilih menerbitkan gerakan. Aksi-aksinya diperteguh oleh semangat keislaman hingga menemukan bentuk sebagai gerakan politik keagamaan. Melaluinya keputusan-keputusan pemegang kekuasaan tidak lagi dihadapinya dengan persetujuan tapi perlawanan. Sikap berlawan ditanam, dipupuk, dan disiram oleh para mubaligh dari tempat peribadatan hingga merebak ke jalanan. Bagi mereka, Rezim Soeharto setelah menyingkiran gerakan politik kiri maka kini memandang gerakan Islam politik sebagai musuh utamanya. Kelompok Islam politik disebut sebagai ‘kelompok ekstrim kanan’ yang harus dimusnahkan, karena tidak mau tunduk pada Orba. Ketindaktundukannya pada negara bukan semata karena ekonomi melainkan berang mendapati kebijakan penguasa yang mensubordinatkan agama: kaum muslim coba dilepaskan dari semangat ideologis agamanya melalui penerapan asas tunggal Pancasila. Hanya kemudian penguasa cepat sekali mengendus gerak-gerik mereka. Pada 8 September 1984 Sertu Hermanu datang ke Mushollah As Sa’adah untuk mengganggu aktivitas politik dan keagamaan warga. Dia bahkan memasuki tempat ibadah itu tanpa membuka sepatu hanya buat memusnahkan pamflet kritis tadi dengan membasahinya menggunakan air comberan. Masyarakat emosi atas perbuatannya sehingga membakar motornya.
Hubungan antagonistik antara negara dengan masyarakat semakin menajam dan mencari mangsa. Akibatnya para penceramah yang berusaha menyiarkan penindasan negara diancam oleh aparat Kodim Jakarta Utara I Kodam V Jaya I Laksusda Jaya. Empat orang di antaranya sampai diseret aparat secara paksa dengan tuduhan melakukan pembakaran kendaraan Hermanu. Mubaligh-mubaligh itu ditangkap dan disiksa. Maka massa melancarkan protes besar yang bukan hanya menuntut pembebasan penceramah melainkan juga seabrek permasalahan lainnya, terutamamenolak asas tunggal Pancasila. Puncaknya adalah malam 12 September 1984: warga mengadakan Tabligh Akbar terbuka. Mereka bergerak menuju Kodim Jakarta Utara untuk membebaskan keempat orang saudaranya yang ditahan. Disarikan dari catatan Komnas HAM, sesampainya di tempat tujuan aparat menyambut dengan ledakan senapan: ‘dari pengakuan korban, segerombol serdadu langsung menembak dengan senjata. Massa yang berada di barisan depan jatuh bergelimpangan berlumuran darah, sedangkan yang lainnya bertiarap dan ada di antaranya yang pura-pura mati. Selain itu, ternyata ada pula korban yang terkena tembakan karena kebetulan sedang melewati lokasi. Dalam kejadian tersebut Komnas HAM RI mencatat jumlah korbannya: 23 meninggal, 36 luka-luka tapi tak dirawat, dan 19 luka dalam perawatan’.
Negara borjuis sangat zalim, sinting, dan menjijikan. Rakyat dibonsai habis-habisan. Segala potensi perlawanan yang dimiliki kaum miskin dan tertindas dilenyapkan. Kesewanang-wenangan pemberlakuaan asa tunggal Pancasila kemudian tidak cuma berhasil menghina, menembaki, dan membunuh masyarakat Tanjung Priok, karena beberapa tahun sesudahnya pasukan bersenjata kembali dikerahkan untuk menerka, meringkus, dan mencabut nyawa ratusan jiwa di Lampung. Lagi-lagi massa-rakyat yang taat beragama diganyang tanpa belas kasihan seperti upaya-upaya membasmi bakteri jalang. Kejadian ini terjadi tahun 1989, dikenang sebagai Peristiwa Talangsari. Pembantaian berlangsung tiba-tiba sewaktu warga melaksanakan ibadah. Walhasil, kegiatan sholat komunitas muslim bukan saja tidak aman tapi terutama diiringi tumpahan darah. Dalam Peristiwa Talangsari, Komnas HAM mencatat: 109 rumah dibakar, 77 warga diusir paksa, 53 orang dirampas kemerdekaannya, 46 disiksa, 268 dianiaya, dan 130 meninggal dunia.Pelakunya adalah negara melalui tangan-tangan TNI-Polri dalam Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas). Para korbannya adalah orang-orang kecil yang menjadi jamaah atau berfiliasi dengan kelompok Warsidi dari Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung. Mula-mula keresahan kelompok ini sama dengan para korban pembunuhan di Tandjung Priok: mempermasalahkan asas tunggal Pancasila dan pelarangan pakaian busana muslimah (jilbab) perempuan.
Persis pembunuhan umat beragam di Tanjung Priok dan Talang Sari, setelahnya Orba juga kembali berulah dengan membunuh pemeluk-pemeluk kegamaan yang taat di Deli. Kejadian itu berlangsung 12 November 1991: dikenal dengan peristiwa Santa Cruz. Di situlah militer bertingkah beringas hingga membunuh massa dengan sadis. Berita pembantaian tersebar ke berbagai penjuru dunia setelah rekaman video dari Max Stahl—mengenai peristiwa ini—diputar di ITV Britania pada Januari 1992. Dalam tayangan yang viral itu terlihat jelas bagaimana TNI-Polri melukai, menewaskan dan menghilangkan paksa petani, buruh, dan terbanyak adalah kalangan mahasiswa. Tragedinya bermula tatkala para aktivis se-Timor menyiapkan demonstrasi menyambut rencana kunjungan parlemen Portugal ke Tim-Tim. Kedatangan pejabat itu membawa kepentingan busuk: perundingan Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Indonesia terkait siapa yang berhak menguasai Tim-Tim. Maka massa-rakyat dengan cekatan menyiapkan spanduk untuk demonstrasi di Gereja Motael, Dili. Hanya saja aktivitasnya dihalangi inteligen Indonesia hingga memicu keributan yang menyebabkan kematian Sebastiao Gomes Rangel oleh tembakan militer Indonesia. Kontan, anggota dewan Portugal membatalkan kunjungannya. Aksi menghadang kedatangannya lalu digantikan dengan mengenang pembunuhan Gomes Rangel dalam bentuk gerakan klandestin: melakukan arak-arakan untuk menaburkan bunga di kuburan Rangel, di pemakamam Santa Cruz. Di situlah suasana duka cita berubah menjadi demonstrasi terbuka. Rakyat dan mahasiswa mengebumikan mayat Gomes tidak sebatas dengan ritual pemakaman, melainkan diiringi protes yang menggelegak kepada kelas penguasa. Pemerintah Indonesia dicaci dan dikutuki. Massa bahkan membentangkan spanduk yang bertuliskan keinginan untuk merdeka: menenutukan nasib sendiri. Penguasa lantas murka. Aparat-aparat bersenjatanya kemudian diperintahkan membrondongi pembangkang dengan peluru. Jumlah korbannya ratusan orang: terdapat 271 tewas, 382 terluka, dan 250 hilang. Seno Gumira Ajidarma mengisahkan kembali tindakan biadab tersebut—dalam Jazz, Parfum, dan Insiden—dengan amat gamang. Lewat salah seorang tokoh di novelnya, dia menggambarkan suasana mencekam saat kesewenang-wenangan hingga kekerasan seksual berlangsung:
“Hari itu ada 3.000 orang di gereja dan sekitar 1.500 orang menunggu di kuburan, karena memang ada pengumuman dari beberapa stasiun radio: akan ada upacara tabur bunga. Jadi semua orang datang, termasuk anak kecil. Perjalanan dari gereja sampai kuburan tidak ada gangguan. Hanya, sampai di markas, katanya ada penusukan seorang tentara. Saya sendiri tidak lihat siapa yang tusuk, banyak sekali manusianya … tidak lama kemudian, tiga truk tentara datang dan baru polisi berani lompat turun dari kendaraan. Di belakang kuburan, kita lihat sudah banyak dikelilingi tentara….Tahu-tahu terdengar tembakan pertama, kita tidak tahu itu tembakan ke atas atau ke mana. Mungkin ke atas yang pertama, setelah itu langsung terdengar rentetan tembakan, selama lima menit lebih. Waktu itu saya berada di tengah. Saya lihat yang di depan berjatuhan semua…. Setelah tembakan antara lima sampai sepuluh menit selesai, mereka blokir sekitar kuburan supaya orang tidak bisa lari. Ketika mereka temukan yang masih hidup, termasuk saya, disuruh telanjang semua, sambil mengancam, ‘Sekarang kamu semua berdoa, waktunya sudah tiba, kamu akan mati semua!’ Saya waktu itu ditelanjangi, kemudian dipukuli pakai kayu, terus salah satu dari mereka mengambil bollpoint yang ada di baju saya, dan memasukkan ballpoint tersebut ke alat kelamin saya. Saya lihat teman di sebelah saya, kepalanya ditusuk pakai pisau.”
Pembunuhan yang dilakukan negara bukan hanya pada peristiwa Petrus 1982-85, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, dan Santa Cruz 1991; karena sampai masa-masa terakhir kekuasaan Soeharto kesewenang-wenangan berdarah semakin melimpah-ruah bagai tumbuhnya jamur di musim hujan. Kekerasan itu masih seperti fenomena-fenomena sebelumnya: di permukaannya nampak dipicu oleh persoalan kriminalitas, keagamaan maupun kebangsaan, tapi di dasarnya bersemayam kepentingan modal dan kekuasaan. Karl Marx pernah mengatakan: ‘akumulasi kapital dimulai dan ditopang oleh sebuah proses yang berdarah-darah’. Ini disebutnya sebagai ‘akumulasi primitif’: ‘adalah proses pemisahan paksa produsen-langsung dari sarana produksi dan sarana penghidupannya yang berakibat pada tertransformasinya sarana penghidupan menjadi sarana produksi dan produsen-langsung menjadi buruh upahan. Dari relasi sosial inilah lahirlah situasi spesifik: kelas yang tidak menguasai alat produksi teralienasi karena kemampuan kerjanya disulap menjadi komoditas yang kemudian disubtitusi oleh kelas yang berkuasa menjadi kapital. Ketika Marx menciptakan teori akumulasi primitif ini fenomena yang dipelajarinya adalah perjuangan dengan kekerasan melawan pengusiran paksa dan perampasan. Dalam sejarah akumulasi primitif, dia memberi contoh terkait apa yang terjadi di Inggris—hampir 400 tahun sejak abad ke-14: akumulasi ini dilaksanakan dengan memagari ‘fasilititas umum’ yang pada awalnya bisa diakses pemanfaatannya oleh siapa saja. Pemagaran itu kontan membuat para petani kecil diusir dari tanah dikerjakannya. Karena tanah yang telah dipagar tersebut dijadikan ladang untuk penggembalaan domba demi memenuhi kebutuhan industri kain akan bulu-bulu domba.
Lantas petani-petani malang tadi yang sudah tidak memiliki sarana produksi dipaksa diperlakukan sebagai tentara cadangan perindustrian yang baru berkembang. Sayangnya mereka tidak bisa langsung beradaptasi dengan kegiatan industri, karena corak produksi modern menuntut keterampilan dan kedisiplinan tertentu. Orang-orang miskin dan tertindas ini kemudian lebih memilih hidup sebagai lumpen-proletariat—gelandangan, pengemis, perampok, dan sebagainya. Maka untuk menertibkan dan menguasai mereka, penguasa pun mengeluarkan undang-undang yang disebut oleh Marx dengan ‘Undang-Undang Berdarah’: aturan ini bertujuan agar para lumpen-proletariat mau menjadi pekerja upahan. Untuk itulah orang-orang yang tak sudi mematuhinya dapat dihukum; mulai dari potong kuping, distempel di dada dengan huruf S sebagai tanda budak (slave) dan huruf V yang berarti gelandangan (vagabond), sampai dihukum mati selaku pengkhianat bangsa. Di rezim Orba, proses penciptaan akumulasi primitif menyeruak ketika Soeharto menggencarkan pembangunannya. Hawa dingin akumulasi primitif terkandung dalam pelbagai langkah yang diambilnya di akhir 1960-an-1980-an. Mula-mula dengan Program Revolusi Hijau maka kehidupan petani diasingkan dari kegitan produksinya di lahan-lahan pedesaan hingga mereka harus memilih: melakukan urbanisasi dan terproletarkan di pabrik-pabrik perkotaan atau menjadi penganggur, gembel, dan penjahat di desa-desanya? Apabila petani-petani itu tidak mau ke kota-kota besar maka akan dipaksa menggunakan Program Transmigrasi. Kebijakan ini bahkan ampuh sekali dalam memisahkan Bangsa Papua dari tanah kelahirannya sekaligus melucuti kekuasaan mereka atas kekayaan alam tanah airnya dengan pelbagai ilusi. Tetapi ketika penduduk asli Papua masih ngotot bermukim di kampung halamannya maka penguasa mulai menggunakan kebijakan kasar: Operasi Militer.
Selama kepemimpinan Soeharto, pengerahan aparatus represif negara untuk melancarkan sirkulasi dan akumulasi modal telah mengakibatkan konflik berkepanjangan bukan hanya di Papua, tapi juga Aceh bahkan di Timur Leste. Dengan operasi-operasi militer itulah kenapa Laut Timor jatuh ke penguasaan Indonesia bersama Australia dan perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi SDA rakyat di Aceh dan Papua semakin berjaya di atas perlindungan negara. Dipertahankannya DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh dan Papua adalah siasatnya. DOM digencarkan di kedua daerah tersebut karena penguasa berniat memuluskan perampokan kekayaan alam yang ada di sana. Di Aceh, mulai 1989-98 Soeharto menjadikan wilayah tersebut sebagai DOM demi melindungi kerja samanya dengan Exxon Mobil dalam menambang gas alam melalui PT Arun dan Mobil Oil Indonesia. Dalam sebuah artikel–Seri Studi Kasus: Stusi Kasus Keterlibatan? Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran HAM DI Aceh—yang diterbitkan ICTJ menjelaskan: bahwa untuk mendapatkan jasa pengamanan dari TNI-Polri makaExxon berani membayar Pemerintah Indonesia lebih dari 500.000 dolar AS per bulannya. Pembayaran tersebut mendukung paling sedikit pelibatan 1000 personil keamanan dari 17 kantor tentara dan polisi. Selama Aceh jadi DOM, aparat-aparat mendapatkan pemasukan tidak saja dari jasa keamanan (bisnis non-institusional) dengan perusahaan tapi juga lewat penjualan senjata. George Junus Aditjondro menyebut perdagangan senjata mereka sebagai ‘bisnis kelabu’ yang sebagian besarnya bersifat illegal; menyangkut penggunaan sarana milik tentara dan polisi, hingga dilindungi oleh senjata militer aktif serta otot para preman.
Dalam Bisnis Perang dan Kapitalisme (2008), terdapat bagian tulisan George Aditjondro yang membeberkan: Di Aceh, penjualan senjata kebanyakan dilakukan oleh aparat-aparat korup dan kadang-kadang dijalankan oleh perusahaan yang legal. Melalui perdagangan seperti ini kalangan serdadu yang rakus bisa berniaga dengan GAM. Sepucuk senapan dapat dibeli dari mereka seharga 50 juta rupiah. Patokan harga yang mahal membuat GAM terpaksa mengumpulkan uang memakai cara ilegal juga: menyelundupkan ganja dari Aceh ke negara-negara tetangga—Muangthai Selatan dan Malaysia. Hanya saja secara periodik TNI-Polri ternyata mampu menghalang-halangi aksi penyelundupan sampai ganjanya disita. Akibat penyitaan, keuntungan besar akhirnya diperoleh pihak aparatus represif negara. Aditjondro berkata: ‘dari situ muncullah lelucon yang beredar di kalangan aktivis perdamaian di Aceh, bahwa “yang datang bawa M-16, pulang membawa 16 M (16 milyar rupiah)’. Namun: meski menjadi patner bisnis ilegal serdadu-serdadu serakah, GAM tetap harus dimusnahkan. Sebab, keberadaan mengancam mengancam sepak terjang modal-asing yang selama ini telah memberikan keuntungan besar kepada pemerintahan. Apalagi untung yang dikutip dari hasil penjualan senjata tidaklah seberapa dibandingkankan anggaran operasi militer dari perusahaan. Itulah mengapa dalam pembasmian GAM, Soeharto tak segan-segan meningkatkan status Aceh menjadi DOM dan mengerahkan ribuan pasukan tambahan. KontraS (2006) melaporkan:
“Pemerintah mulai melakukan upaya penumpasan yang sistematik terhadap GAM sejak 1989 dengan memberlakukan Operasi Militer di Aceh. Sejak itu pula penumpasan itu dilakukan dengan berbagai cara atas nama stabilitas keamanan demi pembangunan. Penumpasan dilegitimasi dengan operasi militer dengan berbagai nama sandi operasi. TNI terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM secara sistematis (tertutup) berupa pembunuhan, penculikan, penangkapan sewenang-wenang tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, penyiksaan bahkan pemerkosaan terhadap para anggota GAM dan warga sipil yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan GAM. Aparat keamanan juga melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk sebagai upaya pemaksaan penduduk untuk mengakui keterlibatannya dalam GAM … penerapan operasi militer ini juga dapat dibaca sebagai usaha pemerintah untuk mengamankan ‘modal’ mereka di Aceh. Awalnya adalah sebuah gerakan sporadis gangguan keamanan dan teror di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie, tempat berbagai sumber daya alam dan industri penting beroperasi…. [Lalu negara] memutuskan menggelar operasi keamanan dalam negeri dengan mengirimkan unit pasukan elite Angkatan Darat (Kopassus), dengan nama sandi operasi “Jaring Merah”. Operasi tersebut bukan operasi tempur melainkan operasi intelijen guna menemukan rantainya dan operasi teritorial guna menarik simpati dari masyarakat…. Setidaknya ada 7 operasi militer yang digelar selama Aceh dalam masa Daerah Operasi Militer (DOM), selain Operasi Jaring Merah, ada Operasi Siwa…. Struktur militer [Komando Teritorial (Koter): Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa)] memungkinkan penerapan strategi militer yang cepat di Aceh yang mencakup pengawasan intensif, pemberlakuan jam malam, penggeledahan rumah, dan penangkapan-penangkapan tanpa dasar yang berskala luas. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM oleh TNI[-Polri] dalam tahun 1989 hingga 1998.”
Melalui praktek kekerasan dan pelanggaran HAM seperti itulah Orba bersama Exxon Mobil mengamankan usahanya di Aceh—PT Arun dan Mobil Oil Indonesia. Bahkan salah satu kamp penyiksaan militer terbesar—sekaligus pusat komando operasi militer (dengan sandi Operasi Jaring Merah)—berada di Rancung: lokasi yang merupakan bagian dari kompleks pabrik besar milik Exxon yang disediakan untuk dipergunakan oleh aparat keamanan dalam melancarkan operasinya.George menegaskan: ‘Exxon Mobil merogoh kantong hampir 5 milyar rupiah setiap bulan hanya buat biaya operasional pasukan keamanan yang disewanya. Dana yang diberikan meliputi: uang saku sebesar Rp 40 ribu per prajurit setiap hari, fasilitas transportasi, kantor pos, barak, radio, telepon, mess, dan sebagainya.’ Termasuk fasilitas berupa buldozer untuk membangun kuburan massal.Selama berlangsungnya DOM itu Forum Peduli HAM Aceh mencatat ada ribuan kasus kejahatan yang dilakukan TNI-Polri. Korbannya juga beribu-ribu: 1.321 orang tewas/terbunuh; 1.958 masyarakat sipil hilang; 3.430 warga disiksa; 128 wanita dan anak-anak diperkosa; dan 597 rumah penduduk dibakar. Di sisi Aceh, Papua telah lebih dahulu digerayangi algojo-algojo bersenjata. Sewaktu Pepera 1969 saja, korban kekerasan maupun pembunuhan militer diperkirakan sudah mencapai 3000 jiwa. Lalu ketika 1978 Papua ditetapkan sebagai DOM, maka kebiadaban semakin menggila. Papua dikukuhkan sebagai tempat operasi militer karena kelas penguasa begitu berhasrat dalam membasmi OPM. Sampai 1981, jumlah OAP (Orang Asli Papua) yang tewas di tangan TNI-Polri meroket menjadi 30.000 kepala. Korban kebanyakan berasal dari kalangan yang tidak bergabung dengan OPM. Kawanan serdadu melukai, menyiksa, dan membunuh mereka dengan mengandalkan prasangka dan tuduhan—terlibat dalam kelompok pemberontak—tanpa secuilpun pembuktian.
Negara begitu agresif menjagal musuh-musuhnya demi mengamankan aktivitas pengerukan kekayaan alam bersama PT Freeport di tanah Papua. Dalam merampok emas dan tembaga di sana, Freeport berani mempekerjakan TNI-Polri sebagai anjingnya. Dalam catatan George Aditjondro: Sejak 1980, Orba menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta dolar AS atas pemberian kesempatan eksploitasi di Papua. Kemudian diatur pula dengan Kepres No. 92/1996, bahwa Yayasan Dana Sejahtera milik Soeharto ikut menerima jatah dari Freeport senilai 20,3 juta dolar AS. Bahkan ketika 1996, dua ribu pasukan tambahan berhasil dikirim ke Papua maka perusahaan langsung membayar jasa pengamanan ini 40 juta dolar AS. Seperti DOM Aceh, dalam DOM Papua juga berlangsung kegiatan bisnis kelabu yang dilakukan aparat keamanan. Dengan bertugasnya 11.500 aparat represif negara dalam berbagai operasi penumpasan OPM sampai tahun 1984 saja, maka sekitar 34.500 ekor burung Cendrawasih telah terkuras dari alam Papua. George Junus Aditjondro menjelaskan: ‘pasukan-pasukan itu tidak punya kesulitan mengangkat satwa langka yang seharusnya dilindungi, sebab mereka dengan mudah dapat menggunakan pesawat Hercules TNI/AU, kapal TNI/AD, serta kapal patroli Polri’.Mereka bahkan mengomersialkan penggunaan pesawat Herculesnya serupa usaha penerbangan pesawat-pesawat regular: tiketnya dijual mulai 200-900 ribu rupiah. Di samping itu serdadu-serdadu ini pun menjual ikan hasil rampasannya dari tangan nelayan, hingga bekerja sama dengan para penebang liar yang memberikannya banyak rupiah. Selama berlangsungnya DOM Papua, kayu gaharu menjadi komoditas yang paling banyak mengisi kantong polisi dan tentara. Konflik yang kerap timbul di antara pencari gaharu dengan penduduk setempat tak dihiraukannya. Aparat justru semakin berfokus mengejar keuntungan dari kekayaan alam Papua. Bahkan untuk memperoleh untung berlimpah serdadu mendorong segenap pedagang gaharu dalam membujuk pemburu gaharu menyepakati sistem barter: gaharu ditukar seks. Pekerja seks komersil (PSK) didatangkan TNI-Polri dari daerah sekitar atas nama bisnis. Meski PSK yang dipekerjakan kebanyakan mengalami HIV/AIDS perbarteran tetap digelar. Akibatnya, pada 1990-an penyakit kelamin mendadak membuat masyarakat Papua gempar. Soalnya barter gaharu dengan seks mempercepat penyakit menjalar. Pertukaran komoditas tidak saja menyebarluaskan sakit tapi amat mengeksploitasi para pengumpul gaharu tadi. Lagi-lagi melalui tulisan hasil penelitiannya Aditjondro memapar begini:
“…pengurasan gaharu telah melecut ledakan HIV/AIDS di Papua…. Di daerah ‘segiempat emas’ perdagangan gaharu di Kabupaten Merauke, yakni distrik-distrik Akat, Agats, Asgon dan Atsy, para pedagang membujuk rayu laki-laki setempat untuk berhubungan intim dengan para pekerja seks, dengan bayaran gaharu. Kedatangan para pekerja seks itu, yang sebagian didatangkan dari Timika, didukung oleh anggota berbagai satuan TNI dan Polri, khususnya Kostrad dan Brimob. Pekerja seks yang direkrut untuk membantu pengurasan gaharu dari pedalaman Papua umumnya adalah mereka yang sudah merosot jumlah kliennya di lokasi-lokasi industri seks di kota-kota Papua, seperti Merauke, Timika, Sorong, dan Jayapura. Dengan demikian, kemungkinan penyebaran penyakit kelamin dan khususnya penyakit HIV/AIDS semakin besar, sebab penyakit HIV/AIDS sudah teridentifikasi diidap oleh pekerja seks di kota Merauke 1992, tiga tahun kemudian di Timika, dan tahun 1998 di distrik Agats…. Kembali ke persoalan gaharu dengan pelayanan seks, kualitas gaharu yang disetor ke pedagang pengumpul, menjadi ukuran seks yang didapat oleh ‘pemburu gaharu’ … dengan pelayan seks tersebut, selain membawa resiko penyakit kelamin, secara ekonomis juga sangat eksploitatif. Apa yang diterima laki-laki penyetor gaharu tak ada artinya dibandingkan dengan 500 ribu sampai lima juta rupiah yang dapat diperoleh eksportir gaharu dari Singapura dan pasaran lain di dunia.”
Di pasar dunia harga gaharu bahkan mencapai 500 dolar AS per poundnya. Inilah yang membuat keluarga istana tertarik memperbisniskannya. Ari Haryo Wibowo (cucu Soeharto) sampai terjun ke Papua Barat bersama pamannya Hotomo Mandala Putra (anak Soeharto) guna memimpin kartel pengumpul gaharu. Dalam mengangkut gaharu dari pedalaman Papua maka lapangan terbang Timika yang dikuasai PT Freeport dipakainya sebagai pos pengumpulan gaharunya. Sejak di hutan sampai tiba ke bandara seluruh aktivitas bisnisnya menggunakan pengawalan total aparat represif negara. Struktur Koter—yang terdiri dari Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa—adalah ahlinya. Di Papua mereka jago sekali melakukan bisnis kelabu. Selain mengutip untung atas hasil hutan, mereka juga mengadakan usaha ilegal di wilayah perairan. Endapan tailing (bahan buangan tambang) yang setiap hari mengendap di hilir Sungai Ajkwa mendatangkan uang bagi satuan Kopassus. Karena para kontraktor penebang pohon mati yang membuang limbahnya di sepanjang hilir itu membayar ongkos perlindungan kepada komplotan serdadu yang sedang bertugas. Hanya saja pemasukan dari bisnis-bisnis kelabu barusan tetaplah tak mampu mengalahkan keuntungan yang diberikan Freeport. Perusahaan ini memberikan 11 juta dolar AS per tahun ke dalam dana kolektif untuk kepentingan militer. Terhadap aparat-aparat pengamannya dijamin pula pembiayaan terkait infrastruktur, makanan dan uang makan, perumahan, angkutan, reparasi kendaraan, membayar pengeluaran kecil dan lain sebagainya. Melalui asupan tersebut negara kemudian mengerahkan 3000-4000 personil TNI-Polri buat memuluskan usaha perampokan SDA dari ancaman OPM.
Dengan pendekatan keamanan-militer, Soeharto terus-menerus menggunakan ABRI (AD, AU, AL, dan AK) dalam mengawal pengerukan SDA Papua sekaligus menumpas gerakan OPM yang mencoba menghalanginya. Operasi militernya dimulai dari 1966/67-1998. Sejak saat itulah Orbamelaksanakan operasi militer sebanyak lima tahapan: dibuka oleh Operasi Bharatayudha (1966-1968) pimpinan Pangdam XVII Cendrawasih Brigjen R.R. Bintaro; dilanjutkan Operasi Wibawa (1968-1969) dari Brigjen Sarwo Edhi Wibowo; disambung lagi Operasi Pamungkas (1969-1973) Brigjen Acub Zainal; empat tahun kemudian dilaksanakanlah Operasi Koteka dan Operasi Senyum (1977-1978) Pangab M. Jusuf; setelah mengendor hampir sewindu barulah diadakan Operasi Gagak (1985-1990) Mayjen Ali Moertopo; dan disusul Operasi Rajawali (1990-1998) Mayjen Abinowo. Sepanjang beroperasinya militer dalam mengamankan bisnisnya di Papua, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Jan Warinussy memperkirakan: jumlah korbannya hampir 100.000 jiwa. Sementara dalam Mencari Jalang Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua, Agus Sumule melacak agak rinci sebagian kasus pelanggaran HAM Berat TNI-Polri: pada 1977 telah dibunuh 126 orang di Asologaiman dan 148 di Wasi, lalu 1979 sebanyak 201 penduduk dibunuh lagi di Kelila-Jayawijaya, dan sepanjang 1980-1995 ada 13 warga hilang dan 80 wanita diperkosa di pelbagai wilayah Papua. Bahkan, sejak pelaksanaan operasi militer Papua petaka mendadak menerpa lingkungan dan penduduk setempat. Apalagi setelah DOM berlaku maka kehidupan warga semakin sekarat. Disarikan dari hasil penelitian Tim Peneliti KontraS; bahwa bisnis institusional, non-institusional, maupun kelabu dari TNI-Polri bersama para pemodal berdampak getir terhadap alam, tumbuhan, hewan dan terutama rakyat. Kolaborasi kekuasaan dan modal soalnya memerosotkan kemampuan ekonomi, menikam keunikan sosial-budaya, dan memangkas kelestarian lingkungan hidup.
Pertama, Dampak Ekonomi. Kerjasama perusahaan dan aparat dalam menguras kekayaan alam mengakibatkan penghasilan masyarakat berkurang. Soalnya kegiatan industri terlalu serakah menyedot hasil hutan hingga penghasilan warga sekitarnya berkurang. Intesifitas penebangan pohon bukan saja mengancam keberadaan fatwa liar, melainkan pula warga: demi kelancaran kegiatan perindustrian maka aparat melarang orang-orang masuk ke hutan. Kerja-kerja berburu dan mencari sagu kontan dianggap mengganggu kenyamanan penebangan pohon. Dalam membatasi masuknya pemburu dan petani ke hutan TNI-Polri menghantamnya dengan alasan mengandung prasangka: kemungkinan mereka akan bergabung dengan OPM sehingga mesti dihalangi. Hanya kalau pekerja-pekerja ini berhasil masuk hutan, aparat kemudian sering kali merampas binatang dan buah-buahan yang didapatkannya. Kedua, Dampak Sosial-Budaya. Dengan berpenetrasinya kepentingan Pemerintah Pusat dan pemodal asing maka OAP—yang tergabung dalam suku-suku atau marga-marga tertentu–kerap terkontaminasi secara budaya. Para pendatang bukan hanya mampu menanggalkan kebudayaan aslinya, tapi juga menyingkirkannya dari tanah-tanah leluhurnya. Bahkan konflik antar-suku dan marga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menguasai hak ulayat mereka. Itulah mengapa adu domba menjadi metode ampuh bagi pemodal dan penguasa dalam menduduki tanah OAP yang kaya hutannya. Ketika konflik pecah TNI-Polri lantas mengamankannya. Tapi kegaduhan justru dimanfaatkannya untuk melucuti kekuasaan masyarakat adat atas tanahnya. Mula-mula aparat kemanan—yang ada di kampung-kampung—mencurigai penduduk, lalu membuatnya was-was, dan tidak bebas bergerak. Inilah mengapa warga-warga mulai merasa tidak nyaman tinggal dikampungnya sendiri sampai akhirnya menyingkir bahkan terdepak. Dan ketiga, Dampak Lingkungan. Usaha pertambangan dan penebangan hutan sedikit sekali diiringi dengan reboisasi. Penebangan pohon pun mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, karena suara bising dan ancaman kematian—penggunaan alat berat dan habisnya makanan—yang ditimbulkannya membuat binatang berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya. Bahkan aktivitas perindustrian yang tak peduli lingkungan ini memicu kelangkaan atau kepunahan pelbagai jenis binatang di Papua. Di Boven Digoel saja, limbah perusahaan-perusahaan telah banyak meracuni air hinggamematikan ikan dan buaya.
Jelaslah sudah: proyeks-proyek pembangunan dan investasi yang digencarkan kelas penguasa bukan membawa kedamaian dan kesejahteraan melainkan keributan dan kerusakan. Bahkan terparahnya adalah kematian-demi-kematian lewat pelbagai kasus kejahatan HAM. Melaluinya Papua, Aceh dan daerah-daerah pemilik SDA lainnya menjadi sasaran keberingasan aparat. Pembangunanisme memorak-morandakan sektor-sektor penting kehidupan rakyat. Dalam Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia (2011), Ahmad Tohari dan kawan-kawannya menjelaskan bagaimana tragisnya nasib rakyat miskin dan tertindas di tangan penguasa dan konglomerat:
“…pada zaman Soeharto itu diselubungi oleh cerita hancurnya mayoritas rakyat Indonesia di kantong-kantong SDA. Mereka dieksploitasi hingga ke bulu-bulunya, dengan mengambil tanahnya, mengeruk mineralnya dengan alasan pembangunan, menanami tanah yang dirampas itu dengan tanaman yang tidak dinikmati hasilnya oleh penduduk setempat dengan alasan peningkatan industri, mengambil kayu-kayu yang ada di sana dengan alasan konservasi, serta membuat orang-orang itu mendekam dalam situasi sulit karena harus bekerja sebagai orang upahan yang untuk biaya hidup sehari-haripun susah. Sebaliknya, di sudut yang lain, proses itu menciptakan tumpukan kekayaan besar di segelintir orang di dalam negeri yang patuh pada Soeharto, dan patuh pada kebijakan-kebijakan liberal yang diterapkannya…. Pada periode 1980-an awal, Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company, dan Inco Ltd, mulai beroperasi di areal-areal tambang strategis. Sementara itu perusahaan-perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) milik keluarga Soeharto mulai membuldozer bukit-bukit di Kalimantan, dan perkebunan besar swasta selain areal PTPN yang terus melanjutkan usahanya sejak tahun 1979 (Konversi Hak Barat). Sementara itu, karakter otoriter yang dilakukan oleh Orde Baru membuat mekanisme partisipasi rakyat tidak banyak terkuak ke publik. Pada zaman Orde Baru kasus konflik dan kekerasan itu telah banyak, tetapi karena kontrol kuat pemerintah terhadap media massa pada waktu itu sehingga informasi-informasi konflik di wilayah-wilayah bersumberdaya alam pada periode 1990-an tidak terlihat kecuali itu ditampilkan dalam wajah yang berbeda. Misalnya konflik SDA di Aceh dan di Papua dikampanyekan sebagai gerakan separatis [Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)] yang harus dibasmi dengan kekuatan Militer. Demonstrasi massa dianggap gerakan subversif dan menentang Negara….”
Kapitalisme-imperialisme telah merampas kedaulatan rakyat atas tanah dan kekayaan alamnya di perkebunan dan hutan-hutan. Keadaan ini membuktikan bahwa akumulasi primitif masih terus mengada dalam kehidupan masyarakat modern. Sepanjang Rezim Orba, badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan tak segan-segan memagari lahan-lahan konsesi, dan mengeluarkan masyarakat adat dari dari wilayah tersebut. Kontan, hubungan dan cara komunitas lokal menikmati hasil dari tanah dan alam menjadi terputus. Penguasa dan pengusaha memutuskan begitu mudah: melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh rakyat melainkan gerombolan kapitalis dan imperialis. Walhasil, fenomena akumulasi primitif mengakibatkan berserakannya orang-orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam: mereka hanya mengandalkan tenaga yang dipunyainya saja, sehingga menjadi pekerja bebas. Kondisi petani-petani miskin di desa-desa sudah begitu mengenaskan karena kekayaan alamnya semakin terkuras dan sumber-sumber mata-pencahariannya dirampas. Susahnya bertahan hidup di pedasaan mendepak sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang udik menuju kota-kota yang buas untuk mengais roti sebagai buruh-buruh yang terhisap. Namun perkotaan masa kini sangat jauh berbeda dengan kota-kota di permulaan perkembangan kapitalisme. Periode ekspansi untuk investasi di sektor-sektor produktif telah berakhir dengan resesi pada 1973-74. Di tahun ini kota-kota di Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, Inggris, dan lebih-lebih Dunia Ketiga mulai terancam oleh terkaman pengangguran massal.
Ledakan ekonomi tahun 1982-90 sama sekali tidak mampu menghentikan pertumbuhan kanker tersebut. Pabrik-pabrik sudah banyak ditutup dan pemecatan-pemecatan menjamur. Di sisinya, ekspansi kredit yang tak-terkendali menjalar ke seluruh dunia seperti jerami yang terbakar dan memperdalam krisis masyarakat kapitalis. Namun bagi kaum intelektual Marxis ini bukanlah krisis kapitalisme tapi hanyalah persoalan neoliberalisme—komersialisasi, privatisasi, dan swastanisasi. Semua masalah kemerosotan yang berlangsung di ujung hidung mereka hanya mampu didekati sebagai masalah-masalah pasar bebas. Upah murah? Neoliberalisme. PHK? Neoliberalisme. Penggusuran? Neoliberalisme. UKT meroket? Neoliberalisme. Gerombolan ini menutup mata kalau dalam kemerosotan ekonomi hari ini telah menyudutkan pemerintah sehingga melakukan campur tangan dengan mengatur bahkan menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta di bawah kendali negara borjuis. Zaman ini adalah zaman imperialisme—zaman krisis kapitalisme, bukan zaman kemahakuasaan pasar bebas. Kekuatan produksi yang dikembangkan kapitalisme telah melampaui batas-batas sempit negara bangsa dan kepemilikan pribadi. Persaingan yang menjadi faktor utama kemajuan kapitalisme telah sampai kepada kesimpulan rasionalnya: monopoli dan ekspor kapital yang menghubungkan seluruh negeri bukan saja dalam sistem perdagangan dunia, tetapi juga bentrokan-bentrokan berdarah dengan selubung ketertiban dan pertahanan nasional. Imperialisme telah menundukkan pusat-pusat politik dan perekonomian nasional dalam jeratan kapital perbankan. Krisis Moneter Asia 1997, yang ikut menerjang Indonesia, sampai meletuskan Krisis Ekonomi 1998—merupakan bagian dari pemberontakan tenaga produktif terhadap batas-batas sempit negara-bangsa dan kepemiikan pribadi. Aksi-aksi protes membara. Dalam kalkulasi pimpinan PRD: menjelang Pemilu 1997, 1 juta massa-rakyat yang muak dengan keadaan telah termobilisasi di seluruh Indonesia. Banyak mahasiswa, dosen, yang selama ini tertidur pulas tetiba berlomba-lomba menggelar mimbar bebas, demonstrasi, sampai berujung aksi massa. Gelombang radikalisasi meluas begitu rupa. Gerakan-gerakan tidak saja dilakukan oleh mahasiswa radikal dan kelas pekerja di pelbagai sektor, tapi juga oleh kalangan intelektual moderat dalam seabrek lembaga di kampus-kampus: SMPT, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sebagainya. Dalam “Peristiwa 27 Juli 1996”, Peter Kasenda mengingatnya: ‘keterlibatan mereka ditengarai oleh krisis ekonomi yang telah menerabas tembok-tembok kampusnya. Di UTS Surabaya, 500 Dari 11.000 mahasiswa menunda pembayaran SPP. Di Unpatti Ambon, 300 dari 8.600 mahasiswa tidak mendaftar ulang karena tidak mampu melunasi SPP. Masalah serupa juga menimpa mahasiswa di Unibraw Malang, UGM Yogyakarta, dan lain-lain’.
Bersama gerakan dari dalam-dalam kampus yang mulai bangkit inilah aktivis-aktivis PRD mandapatkan tambahan kekuatan dalam menekan kekuasan. Tetapi Orba membalasnya dengan melakukan penculikan-demi-penculikan. Pada 1997-1998, Soeharto mengerahkan Tim Mawar yang dipimpin Prabowo Subioanto untuk menculik dan menghilangkan orang-orang secara paksa. Titik operasinya meliputi: Lampung, Jakarta, dan Solo. Korbannya berjumlah 23 orang: Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser—13 aktivis ini dilenyapkan hingga tak tentu rimbanya; sedangkan 10 lainnya beruntung dilepaskan: Mugiyanto, A’an Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, ‘St’. Dihadapinya gerakan dengan kekerasan terbuka menandakan Tim Mawar pimpinan Prabowo Subianto—yang dibentuk Orba untuk meredam perlawanan rakyat melalui penculikan dan penghilangan paksa—gagal memenuhi harapan penguasa. Itulah kenapa setelah puluhan aktivis yang dianggap memimpin perlawanan ditindas dan dilenyapkan, tapi mimbar bebas, demonstrasi, dan aksi massa tidak langsung mereda. Bahkan sampai Maret 1998 saja, mahasiswa-mahasiswa radikal berhasil melangsungkan 247 aksi protes. Menghadapi tekanan iniah kekuasaan kemudian melancarkan kekerasan-demi-kekerasan. Peter Kasenda merekamnya demikian: ‘Mei 1998, demonstrasi mahasiswa sudah memasuki minggu ke-10. Tidak ada tanda-tanda bahwa aksi protes mahasiswa ini menjadi surut, baik karena kelelahan maupun karena represi. Sebaliknya, represi brutal kalangan militer justru memancing aksi-aksi protes mahasiswa yang kian meluas. Terhitung dari tanggal 1-30 Mei, tercatat lebih dari 445 demonstrasi yang merata di seluruh Indonesia. Salah satu insiden yang menambah besar gelombang perlawanan adalah peristiwa terbunuhnya 4 orang mahasiswa Univesitas Trisakti: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Pada 12 Mei 1998, keempat anak muda ini tewas tertembak di dalam kampusnya. Peluru tajam aparat mengenai tempat-tepat vital mereka: kepala, tenggorokan, dan dada’.
Dalam Peristiwa Trisakti: mahasiswa sebenarnya mengadakan aksi damai dengan melibatkan 6000 massa di kampusnya. Namun penguasa justru membubarkan aksi melalui penindasan menggunakan pasukan bersenjata. Selain empat mahasiswa, brutalitas TNI-Polri juga mengakibatkan 681 orang mengalami luka-luka. Setelah kebuasan serangan aparat di Universitas Trisakti maka keprihatinan dunia internasional bermunculan, lalu investor makin banyak yang lari mengamankan asetnya, kemudian nilai tukar rupiah terus menurun, hingga harga sembako bertambah kemahalan. Walhasil, kemarahan di segala penjuru berkecamuk tak tertahankan. 13 Mei 1998, lebih dari 32 aksi demonstrasi di pelbagai kota serentak diadakan. Ini terutama sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan terhadap para korban yang telah dilenyapkan dan dilukai. Unjuk-unjuk rasa sesudah kematian 4 orang mahasiswa tadi pun bukan hanya menggoncang kekuasaan tapi juga menimbulkan rusuh dari tanggal 13-15 Mei. Kerusuhan massal terjadi di beberapa kota secara bersamaan: riuh dengan tindakan pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Unsur utama pemicu kerusuhan yakni aktivitas para penyusup dalam berlangsungnya gerakan perlawanan. Orang-orang yang tidak dikenal penduduk setempat itu terutama merupakan preman-preman bayaran: kelompok paramiliter. Dijelaskan oleh Peter Kasenda:‘mereka hadir ke jalanan bersama kelompoknya menggunakan bus maupun truk, lalu meneriakan slogan anti-Tionghoa, dan memprovokasi massa secara vulgar. Provokator-provokator itu mempunyai ciri-ciri: berseragam SMA, berjaket mahasiswa, berpakaian lusuh dan berwajah sangar, berbadan tegap [ada pula yang bertato], berambut cepak [potongan rambut khas serdadu], dan bersepatu tentara’. Kala itu sepak terjang mereka menjadi anjing penjaga kekuasaan. Penjagaan yang dilakukannya tak sekedar di gerbang istana melainkan pula langsung bercokol dalam relung-relung parlemen. Ketika mimbar bebas terjadi di pelbagai kampus, protes merebak ke segala penjuru, hingga terbitnya aksi massa—kelompok paramiliter peliharaan rezim ini semakin bertambah besar. Unsur yang paling bertanggung jawab dalam merekrut, melatih, memobilisir, dan melindunginya adalah tokoh-tokoh kemiliteran. Dalam “Pemuda Pancasila dan Rezim Represif Orde Baru”, Abdul Arief menjelaskan demikian:
“…banyak sekali Ormas-ormas kepemudaan yang lahir dari kalangan pemerintah Orde Baru untuk melindungi kinerja pemerintahan mereka. Dalam konteks ini, kita bisa lihat pada masa Orde Baru, rezim Soeharto memobilisasi preman-preman lokal ke dalam organisasi-organisasi seperti Pemuda Pancasila. Langkah ini ternyata berguna untuk mematahkan pemogokan atau untuk membubarkan demonstrasi pihak oposisi dan mengumpulkan masa pada rapat-rapat umum pro-pemerintah pada waktu pemilihan umum. Pada akhirnya para pemimpin organisasi-organisasi tersebut menjadi mahir dalam mencari sumber daya dari pihak penguasa berupa pemberian-pemberian, pekerjaan atau kontrak-kontrak pemerintah. Ratusan pemimpin dan alumni Pemuda Pancasila dan organisasi-organisasi sejenisnya kini duduk diparlemen sebagai anggota terpilih sebagai pemimpin di tingkat pusat maupun lokal, mereka memanfaatkan koneksi-koneksi mereka dengan pihak militer dan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas serta sering menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membangun mesin politik disemua tingkatan pemerintahan dan partai. Ketika oposisi terhadap rezim Soeharto semakin kuat dan terbuka, jumlah dan variasi kelompok-keompok preman pembela kepentingan keluarga Soeharto semakin bertambah. Dalam kapasitasnya sebagai Danjen Kopassus, Letjen Prabowo Subianto yang pada waktu itu mempunyai peranan besar menumbuhkan kelompok-kelompok tersebut. Mulai dari kelompok Anak-anak Tidar, yakni sejumlah lulusan Akabri Darat di Magelang. Ada pula Prabowo dan kawan-kawannya sesama anggota seperti Mayor Jendral Zaky Anwar Makarim, juga sudah menjadi pelindung bagi sekelompok pemuda asal Timor Leste di Jakarta, yang dipimpin pemuda bernama Hercules.”
Untuk menghadapi aksi-aksi perlawanan massa-rakyat negara sepertinya bukan hanya berusaha membubarkannya dengan moncong senjata, tapi juga melalui upaya-upaya pengacauan melalui provokasi. Walhasil, korban dalam Kerusuhan Mei 1998 amat berlimpah; yang tewas saja antara 300-1000 warga. Hanya provokasi dan pengambinghitaman gerakan saat Mei 1998 tidak membuat mereka mengendorkan perlawannya. Bahkan setelah kerusuhan itu gerakan mahasiswa dan pelbagai aktivis lintas sektoral justru berbondong-bondong mendatangi gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Tanggal 18 Mei, jumlah massa yang terus bertambah membuat DPR/MPR dibuat kikuk. Maka sejumlah besar mahasiswa diijinkan masuk ke dalam halaman kantor parlemen supaya pengendalian keamanaan lebih mudah dilakukan aparat-aparat penguasa tiranik. Di antara mereka yang diberi kesempatan berada di halaman parlemen juga nampak kalangan Pemuda Pancasila (PP). Keberadaan organisasi paramiliter ini bertujuan mendukung Soeharto agar tetap berkuasa. Untunglah pasukan pengamanan yang bertugas mengusirnya keluar, sehingga PP tak sampai bentrok dengan mahasiswa. Maka aspirasi berisi tuntutan-tuntutan menekan yang diarahkan langsung di hadapan parlemen Senayan mampu meluluhkan pimpinan wakil rakyat. Itulah mengapa Ketua DPR Harmoko kemudian meminta Presiden Soeharto segera mengundurkan diri. Pernyataan sikap ini langsung disiarkan media massa secara luas. 20 Mei, empat belas menteri dalam Kabinet Pembangunan VII yang baru dibentuk Soeharto was-was membaca situasi yang makin panas. Mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan tuannya.Hanya dalam menyelamatkan takhtanya, Soeharto lantas membentuk Komite Reformasi tapi tokoh-tokoh masyarakat tak mau duduk di dalamnya. Menyadari kekuasaan hegemoniknya telah luluh-lantah, maka dia pun berencana meninggalkan kursi kepresidenannya. Sehari kemudian penguasa Orba membacakan pernyataan mundurnya: ‘Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya becakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998’.
Namun kejatuhan Soeharto tidaklah berarti menuntaskan reformasi dengan revolusi demokratik: penggulingan tiran melalui persatuan demokratik dengan borjuis-nasional ‘progresif’ dan membangun kekuasaan atau demokrasi rakyat miskin seperti yang dicita-citakan PRD. (Ini adalah sesuatu yang secara teori keliru dan dalam praktiknya akan melemparkan massa ke mulut reaksi—ini tidak untuk dibahas di sini, karena telah banyak di bahas di artikel lainnya.) Maka memasuki masa transisi sisa-sisa kekuatan lama—baik kaum moderat maupun konservatif—berhasil mengambilalih kekuasaan di tengah kekosongan kepemimpinan proletariat. Mereka memicu polarisasi politik nasional yang begitu rupa. Gerakan mahasiswa radikal diterabas olehnya. Dan segera setelah Soeharto dilengserkan, semua sisa-sisa rezim lama mengenakan jubah reformis dan mengusung BJ Habibie untuk berkuasa dalam pemerintahan transisi. Keputusan ini diambil demi memotong segala kemungkinan pendirian Dewan Rakyat. Digantikannya Soeharto oleh Habibie tidak melahirkan perubahan fundamental dalam kehidupan rakyat. Itulah mengapa kebusukan-kebusukan Orba masih ditambat. Termasuk soal kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat. Pada 6 Juli 1998 terjadi Tragedi Biak Berdarah di Papua: 500-1000 orang Papua yang menuntut diberikannya kemerdekaan kembali dihadapi dirobohkan dengan senjata. Menjurus ke kejadian itu, Tim Advokasi ELSAM (2015) melaporkan jumlah korbannya: 8 meninggal dunia, 3 hilang, 4 luka berat, 33 luka ringan, 50 ditahan secara sewenang-wenang dan mendapatkan penyiksaan, dan ditemukan 32 mayat misterius. Lalu di tanggal 13-14 November 1998 meledak pula Tragedi Semanggi I. Kala itu gerakan rakyat yang memancang mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan pewaris rezim lama diredam dengan senjata. TNI-Polri kembali menyerang massa-rakyat secara membabi buta. Puluhan ribu demonstran dibubarkan menggunakan nyalak senapan, gas air mata, dan kendaraan lapis baja. 10 orang kemudian meninggal dunia: 6 mahasiswa, 2 pelajar, 1 satpam kampus, dan 3 masyarakat umum—di dalamnya terdapat anak berusia enam tahun: Ayu Ratna Sari, meninggal setelah terkena peluru tajam dikepalanya.
Disetirnya Pemerintah Habibie oleh kekuatan-kekuatan rezim lama tambah kentara saat negara mengeluarkan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Dengan gerakan-gerakan rakyat yang tak pernah menyerah, maka pemerintahan baru melindungi kekuasaannya memakai metode Orba. Inilah kenapa ketimbang mundur secara damai, penguasa yang ditekan justru bereaksi menggila: UU PKB dikeluarkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada militer membasmi semua elemen radikal. Pada 23-24 September 1999, meletuslah Tragedi Semanggi II. Dalam peristiwa ini gerakan rakyat menuntut dihukumnya para penjahat HAM dan dicabutnya aturan keadaan bahaya. Setelah bergulirnya reformasi, semua kasus Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Orba serta bagian-bagian rezimnya yang bergabung dengan pemerintahan Habibie belumlah sama sekali dituntaskan. Daripada mengadili semua penjahat HAM, negara lagi-lagi menambah daftar kejahatan kemanusiaan. Tugas birokrasi bukanlah menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang sejati, tetapi nelindungi segenap kepentingan material dari kelas pemilik yang angkuh dan tambun. Demikianlah di bawah rezim borjuis yang paling demokratis sekalipun, demokrasi dan hak asasi yang dibicarakan hanyalah omong kosong yang berusaha menyelubungi kediktatoran bisnis besar. Papua adalah salah satu bangsa yang sampai sekarang dipaku-mati di altar kapitalisme-imperialisme. Tanggal 7 Desember 2020 menyalak Tragedi Abepura Berdarah: diperkirakan korbannya mencapai 105 orang sipil. Komnas HAM mencatat apa yang mereka alami: 1 cacat seumur hidup karena disiksa dan 1 lainnya juga mengalami kecacatan abadi lantaran ditembak, 1 dibunuh secara kilat, 24 dianiaya—berdasarkan jenis kelamin, ras dan agama—hingga dua di antaranya mati tak kuat menahan siksa. Sedangkan terkait kekerasan tersebut KontraS mendata: 3 mahasiswa tewas akibat penganiayaan dan penembakan, 63 luka berat, dan 15 menderita cacat tubuh serta mental oleh penyiksanaan.
Tanggal 13 Juni 2001, kembali terjadi pembantaian dalam Tragedi Wasior Berdarah. KontraS mencatat jumlah korban jatuh: 4 meninggal dunia, 5 dihilangkan paksa, 39 disiksa hingga luka-luka, dan 1 perempuan diperkosa. Kemudian 4 April 2003 menyusul Tragedi Wamena Berdarah. Untuk ini Komnas HAM mendata korbannya: 25 kampung diserang dan warga-warganya diusir hingga 42 orang diantaranya tewas karena kelelahan dan kekurangan makanan, 15 dirampas kemerdekaannya penuh kesewenang-wenangan, dan 30 disiksa sampai pelbagai luka ditimbulkan. Dan oleh Amnesty Internasional diberitahukan pula tentang Pembunuhan Ekstra-Yudisial yang dilakuakan oleh TNI-Polri di Papua: sepanjang 2010-2018, ditemukan 69 kasus dengan 95 orang menjadi korban pembunuhannya. Pada 2020, diberitakan 1 pendeta dan 1 bocah perempuan tewas diterkam tentara. Di Papua, kini kekerasan masih mendakwah beringas. Negara Indonesia bukan hanya menindas West Papua dengan melancarkan rasisme dan kepentingan nasional, tapi bahkan menyaru kekerasan kapitalisme melalui Otonomi Khusus (Otsus). Alih-alih membiarkan rakyat Papua menjadi bangsa yang dapat menentukan nasibnya sendiri, negara ini justru terus-menerusnya memperlakukannya sebagai budak yang diperas sampai tetes keringat dan darah terakhir. Tahun 2024, kekerasan-demi-kekerasan negara masih berlangsung di mana-mana. Proyek Strategis Nasional adalah salah satu kepentingan borjuis yang dapat memicu ledakan kekerasan negara lagi dan lagi; di mana segala bentuk kekerasan negara borjuis berakar dari ketidakadilan di basis produksi kapitalisme yang dilayaninya. Dan kekerasan negara yang tiada berhenti ini akan memancing perlawanan dan pemberontakan yang terus-menerus dari orang-orang yang berkeinginan keras untuk memperjuangkan penghancurannya.