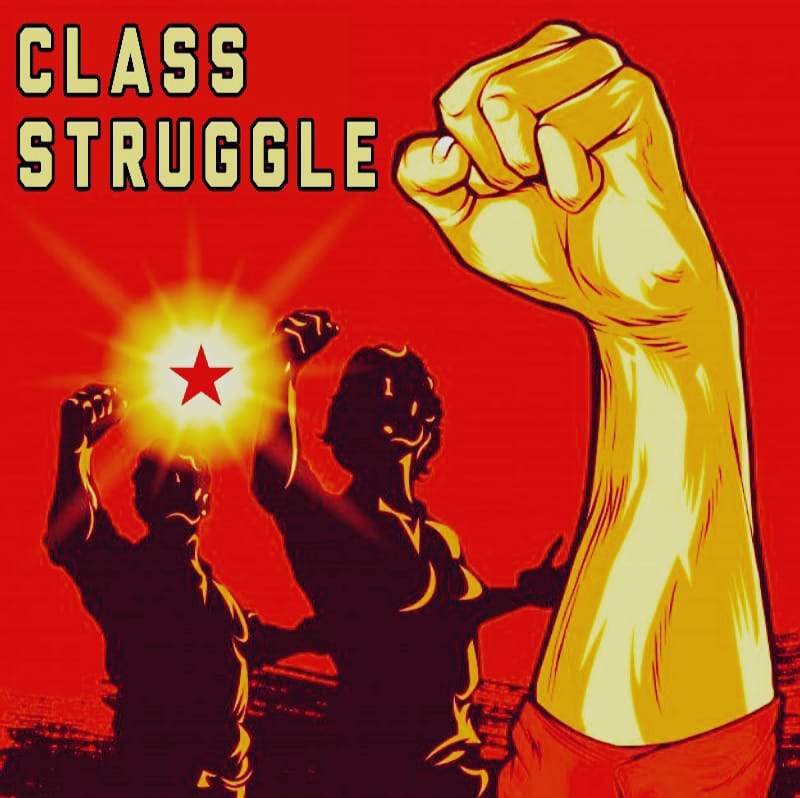“Senioritas, patronase, dan beragam bentuk perbudakan modern tidak terpikirkan tanpa melewati hubungan-hubungan produksi tertentu dan kerja manusia yang bersifat sosial—tidak ada pembebasan massa-manusia dari eksploitasi dan ketertindasannya tanpa perjuangan yang sadar: perlawanan, pembangkangan dan pemberontakan yang positif, terorganisir dan terencana untuk menggulingkan sistem sosio-historis yang kejam dan sedang sekarat ini–masyarakat kapitalis–dan membangun dunia di mana kemanusiaan mendapat tempat untuk tumbuh dan bermekaran dengan sepenuhnya.” (Kamerad)
Selamat datang mahasiswa angkatan baru! Sekarang kamu memasuki kampus impianmu. Tempat ini bukan hanya jadi taman bersemainya ide dan gagasan memukau, melainkan pula arena berlangsungnya aneka lomba. Itulah mengapa sejak kehadiranmu lembaga pendidikan kontan menggelar ospek yang begitu rupa: kalian tak sekedar dijejali aturan busana dan tata-tertib apa saja, melainkan pula dimotivasi mengejar nilai tinggi, meraih onggokan prestasi, wisuda secepat kilat, dan hidup mapan akhirnya. Atas kredo inilah kampus meng-ospekmu dengan memamerkan mahasiswa-mahasiswi yang berpenampilan rapi dan bersih, mempunyai jabatan tertentu dan seringkali mendapat juara. Mereka umumnya berasal dari organisasi-organisasi mahasiswa yang melayani kepentingan lembaga pendidikan semata: melaksanakan seminar, kuliah umum, latihan kepemimpinan, hingga melancarkan segala bentuk pengawasan terhadap mahasiswa. Hanya kepada kalian kampus memperkenalkan mereka sebagai prototip sempurna. Kampus sengaja menempatkan mahasiswa-mahasiswa pilihannya di atas panggung ospek tak sebatas memberi ceramah, tapi terutama untuk ditiru dan digugu oleh mahasiswa angkatan baru semua. Saking lama mendengar retorika mereka, maka kalian terpesona hingga terbius juga. Mula-mula kalian termakan kekuatan tanda yang disematkan pendidikan borjuis kepada mahasiswa yang menjadi panitia ospek-nya. Lihat saja bagaimana kampus mengemas citra panitia ospek begitu rupa: mereka kerap kali diasosiasikan sebagai mahasiswa baik (berdisiplin), sopan (tunduk dan patuh), rajin (penurut dan pembebek), cerdas (bernilai tinggi), dan berprestasi (memperoleh juara). Singkatnya, kampus menginginkan kalian seperti mereka-mereka ini. Lebih-lebih untuk menjadi penggugu hingga mudah dikontrol dalam melancarkan kepentingan birokrasi-borjuasi.
Itulah mengapa ketertiban, ketaatan dan kedisiplinan selalu menjadi prasayarat menjadi panitia ospek. Sebab peran mereka bukan hanya meng-ospek mahasiswa angkatan baru, tapi lebih-lebih menjadi monumen sosialisasi kampus berkait mahasiswa macam apa yang ingin dibentuk. Bahkan ditempatkannya mereka sebagai pusat perhatian saat ospek tidak sebatas menjadi cara naïf kampus meyakinkan kalian semua, melainkan pula mulai mengawasi dan melatih siapa-siapa yang di-ospeknya untuk disiplin, taat, dan tertib. Hanya kontrol ini dilakukan secara samar-samar, terutama melalui pengemasan tanda begitu rupa. Inilah mengapa kampus menampilkan panitia ospek sebagai mahasiswa-mahasiswa senior yang harus dituruti dan diikuti segala arahan mereka ketika ospek menggema. Melalui taburan citra inilah sejak awal kampus menempatkan panitia ospek sebagai senior dan menyulap mahasiswa angkatan baru menjadi junior. Soalnya kala itu status senior dan junior bukan saja dipandang dari siapa yang lebih lama kuliah atau lebih besar usia, namun dibagi oleh suntikan prestise dari kampus. Itulah mengapa panggung ospek yang disediakan kampus tidak sebatas menjadi ajang perkenalan akademik, tapi lebih-lebih menundukan mahasiswa angkatan baru pada panitia ospek (mahasiswa angkatan lama) yang tampil sebagai senior yang mengatur-atur. Pada kondisi inilah ditampilkannya panitia ospek dengan citra mahasiswa sempurna untuk dikonsumsi mahasiswa angkatan baru menampak sebagai fenomena manipulasi tanda. Dalam Galaksi Simulacra (2001), Jean Baudrillard menyebut situasi itu sebagai ‘hipermodernitas’ atau ‘radikalisasi modernitas’, yang membuat manusia terjerat dalam konsumerisme tanda:
“Masyarakat konsumerisme merupakan tatanan manipulasi tanda. Praktik tanda mengarahkan juga konsumsi akan gambar, fakta, dan informasi. Konsumsi ini menyamakan yang riil dalam tanda-tanda riil, menyamakan sejarah dalam tanda-tanda perubahan.”
Pengemasan tanda menggantikan realitas berlangsung dalam arena ospek. Makanya ospek tak sebatas ajang pengenalan akademik, tapi lebih-lebih monumen kontrol dan pengawasan yang hegemonik. Dipasangnya seabrek panitia ospek dengan onggokan citra memukau menjadi bukti bagaimana berlangsungnya manipulasi tanda. Lebih-lebih untuk menatar mahasiswa angkatan baru dalam kubangan disiplin, kepatuhan dan ketaatan seperti para panitia ospek-nya. Dengan citra sempurna yang dilekatkan kampus pada mereka itulah dominasi tidak dijulurkan melalui kekerasan langsung, melainkan bujuk-rayu dan tipu-daya panitia ospek—kekerasan-simbolik. Baudrillard menjelaskan: arena konsumsi memang berlangsung dalam medan sosial yang terstruktur’. Artinya, konsumsi budaya (pengetahuan dan pengalaman) selalu melalui kelompok yang menjadi modelnya. Persis inilah panitia ospek dijadikan patokan—prototip mahasiswa-mahasiswa yang diinginkan kampusnya. Konsumsi yang dilakukan mahasiswa angkatan baru terhadap aneka citra yang disematkan kepada panitia ospek sesunggunya bukanlah kebutuhan dasar, melainkan demi memenuhi tekanan psikologis, ekonomi, sosial dan budaya. Pendorongnya adalah tuntutan mobilitas sosial, status, dan persaingan dalam segala bidang kehidupan masyarakat kapitalis. Logika sosial konsumsi bukan terletak pada kepemilikan nilai-guna tapi logika produksi dan manipulasi yang bermakna sosial. Itulah yang merayu, menipu, dan menyeret mahasiswa angkatan baru berkeinginan memiliki citra seperti yang didapatkan panitia ospek-nya. Hanya untuk beroleh citra itu kalian dituntun menaati dan menuruti arahan gerombolan tukang ospek-mu. Sebab cuma dengan meniru panitia ospek yang berdisiplin, tunduk dan patuh pada birokrasi kampus itulah kalian merasakan telah menaiki tangga kelas sosial tertentu. Dalam kondisi inilah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kalian membentuk citra yang selanjutnya menampilkan klasifikasi dan diferensiasi sosial. Artinya apa yang melekat pada diri kalian sebagai tanda itu dirasakan menjadi sebuah nilai yang menentukan status dalam hirarki sosial. Singkatnya: dengan mengonsumsi bujukan menjadi taat, tunduk dan patuh maka kalian bukan saja merasa telah diterima dalam lingkungan kelompok dominan, tapi juga bersensasi atau memproyeksikan diri (diferensiasi) sebagai bagian kelompok dominan. Memang dalam logika tanda, nilai tidak terletak pada fungsi-kegunaan menjawab tuntutan sosial. Inilah mengapa bukan kenikmatan atau kepuasan yang menjadi prioritas, tetapi fungsi kolektif. Haryatmoko melalui karyanya—Dominasi Penuh Muslihat (2010)—melukiskan itu semua dengan cukup baik:
“Konsumsi adalah sistem yang menjamin tatanan tanda-tanda untuk memenuhi tuntutan integrasi kelompok. Konsumsi itu sekaligus sistem nilai ideologis dan sistem komunikasi karena membentuk struktur interaksi sosial. [Dia memberikan menggambarkan seperti ini:] ketika hari lebaran pulang kampung dengan mengendarai mobil BMW dan membangun rumah besar di kampong asal, inisiatif untuk mengumpulkan ‘trah [keluarga besar satu keturunan]’ tentu akan mendapatkan sambutan luas dari anggota-anggota lain. Barang yang Anda miliki menempatkan Anda pada posisi yang mungkin akan mendapatkan pengakuan sosial.”
Dalam suasana ospek; hubungan sosial yang diikat dengan kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan menjadi bentuk material dari tatanan tanda yang dibangun oleh kampus melalui seabrek panitia ospek. Dibandulinya aktivitas ospek di bawah kedigdayaan tanda kemudian menjadi ajang penyangkalan terhadap yang riil, karena dengan disiplin, taat dan patuh seseorang akan cenderung merasa aman. Gejala seperti inilah yang disebut Baudrillard dengan hipermodernisme: ‘ditandai oleh konsumsi yang telah meninggalkan logika kebutuhan’. Hidup manusia didikte oleh obyek karena harus mengikuti ritme kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan yang telah berubah jadi tanda yang bermakna sosial. Baudrillard menjelaskan bahwa pergantian tanda terus-menerus mengubah pola hubungan antara konsumen dan obyek konsumsi. Konsumen tidak lagi mengonsumsi sesuatu berdasarkan manfaat yang terkandung di dalamnya, tetapi berdasarkan soal pemaknaan keseluruhan obyek yang diatur penataan tanda dengan tujuan sederhana: meningkatkan status sosial atau untuk dapat diterima oleh kelompok dominan semata. Sisi negatif dari konsumerisme mendorong mahasiswa angkatan baru menjadi individualis sehingga mengikis solidaritas. Makin konsumen cenderung soliter maka semakin lemah mereka untuk mengorganisir perlawanan atau mengindentifikasi siapa yang menjadi penindas. Itu sebabnya kalian begitu konformis terhadap citra yang ditawarkan birokrasi kampus. Makanya kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan menjadi nilai yang terus-menerus dikonsumsi hingga kokoh dinobatkan sebagai tradisi bukan hanya saat ospek, melainkan pula jauh seterusnya. Sistem konsumsi dalam kehidupan sosial-politik yang begitu kemudian bisa bertransformasi ke bentuk ideologi. Itulah kenapa konsumsi melembagakan kode nilai yang membedakan dan menentukan interaksi dan komunikasi antar-mahasiswa angkatan baru dengan angkatan lama. Sistem ini mengandalkan mesin integrasi dan regulasi yang tidak disadari. Tengoklah bagaimana tanda-tanda dalam ospek dan kepanitiaan dikonsumsi bukan untuk mendapatkan kepuasan, melainkan kenaikan status dan penerimaan pada lingkungan sosial tertentu. Itu jugalah yang terjadi ketika panitia ospek ditampilkan sebagai prototip sempurna: kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan dibayangkan dapat meningkatkan status sosial atau menjadi prasyarat diterimanya dalam lingkungan kelompok dominan—birokrasi-borjuasi.
Kini kita mengerti bahwa konsumerisme tanda saat ospek didorong oleh narsisisme yang bukan dalam arti kenikmatan diri, tetapi cermin dari wajah kolektif. Pada saat inilah berlaku apa kata Emile Durkheim: ‘yang kudus adalah bentuk ketakutan kepada yang kolektif’. Melaluinya konsumsi tidak digerakkan oleh diri sendiri, melainkan kelompok elit. Fenomena ini menampak ketika mahasiswa angkatan baru amat konformis dengan nilai-nilai yang ditabur panitia ospek dan birokrasi kampus. Dengan mendekatkan ideal kepada dirinya, maka mahasiswa angkatan baru seolah memiliki motivasi sendiri untuk berdisiplin, taat dan patuh. Padahal kaadaan itu telah membuat dirinya mematuhi dengan lebih baik apa yang menjadi tuntutan kolektif dari kelompok dominan. Makanya ketika konsumsi dianggap distimulasi oleh pribadi sendiri, berarti perilaku konsumtif tidak perlu lagi menghadapi ancaman yang berarti. Kondisi itulah yang disindir Baudrillard dengan ungkapan menusuk: ‘merayu diri adalah konsumsi sempurna, meski sebetulnya acuannya tetap yang lain’. Dengan begitu ospek seiras pentas iklan saja: setiap adegan, gambar dan informasi selalu mendakukan persetujuan yang arbitrer. Artinya dengan membaca pesan yang disampaikan kelompok dominan, maka kita akan mengikuti secara otomatis kode—kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan—yang telah dibaca tersebut. Dalam kondisi inilah panitia ospek tidak saja tampil sebagai mahasiswa angkatan lama, tapi juga senior dari mahasiswa angkatan baru. Begitulah struktur senior-junior terbentuk. Inilah mengapa relasi senior-junior (sistem senioritas) bukan terbentuk secara niscaya, karena kelahirannya melalui jalur yang artifisial dan sarat tipu daya. Seiring dengan berjalannya ospek, maka ditampilkannya relasi antara panitia ospek (senior) dengan mahasiswa angkatan baru (junior) menghasilkan budaya senioritas. Dalam Pokok-Pokok Materialisme Historis; Pandangan Marxis terhadap Sejarah dan Politik (2013), Doug Lorimer menjelaskan apa yang dimaksud kebudayaan dengan perspektif sosio-historis—lebih-lebih budaya dari kaum intelektual dalam masyarakat berkelas:
“Konsep kebudayaan berhubungan dengan pengetahuan manusia dan pengalaman dalam satu atau lebih bidang aktifitas, asimilasi mereka dan penerimaan sistem nilai tertentu. Setiap individu dari awal masa mudanya berada di bawah pengaruh kebudayaan tertentu—objek-objeknya, ide, nilai, dan standar tingkah laku. Asuhan dan pendidikan individu terdiri dari, faktanya, adaptasi mereka pada kebudayaan yang ada, dalam mengasimilasi pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang ditumpuk oleh masyarakat, dan juga nilai intelektualnya dan standar tingkah laku. Asuhan dan pendidikan, perkembangan sistem pendidikan publik adalah dalam dirinya sendiri indikator tingkatan kebudayaan masyarakat tertentu. Kebudayaan intelektual memikul cetakan ciri-ciri khas dari formasi sosio-ekonomi tertentu klas-klas yang menciptakannya. Dan dalam pengertian ini hal tersebut berhubungan dengan suprastruktur yang berdiri pada basis ekonomi tertentu…. Hubungan antara klas meninggalkan sebuah kesan penting pada isi kebudayaan intelektual dalam sebuah masyarakat yang terbagi dalam klas. Ini berarti bahwa ideologi adalah sebuah elemen yang sangat penting sekali dalam kebudayaan apapun. Kebudayaan juga memanifestasikan ciri-ciri spesifik psikologi sosial yang merupakan karakteristik dari jaman atau sebuah klas.”
Ketika pelaksanaan ospek maka kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan menampilkan bentuk kesatuan sosial atau karakteristik tatanan senioritas yang dibangun untuk menyangga kekuasaan birokrasi-borjuasi. Begitulah masa pengenalan kampus yang sesungguhnya dapat memenuhi kebutuhan informatif mahasiswa angkatan baru disulap jadi arena penanaman ide, nilai, dan standar tingkah-laku yang melayani kepentingan kelas borjuis. Dipanggungkannya panitia ospek sebagai spesies yang patut ditiru dan digugu merupakan momen disuntikannya kebudayaan senioritas. Keadaan ini memberitahu kita bagaimana budaya senioritas berdiri di atas prestise bentukan birokrasi-borjuasi. Maka kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan yang mereka suntikan melalui segala aktivitas (sosialisasi nilai) saat ospek kalian akan sangat berbahaya apabila dianggap sebagai kebutuhan mahasiswa. Sebab logika konsumsi di balik citra ini tidak terletak pada nilai-guna atau kepuasan, tetapi logika produksi (kapitalisme) dan manipulasi tanda yang digunakan kampus untuk melumpuhkan kesadaran, radikalisasi dan militansi mahasiswa. Tujuan utamanya sangat gila: membiasakan mahasiswa untuk berdisiplin, diatur, dan taat pada norma-norma borjuis agar mudah disiapkan menjadi tentara cadangan industri bergaji murah nantinya. Inilah mengapa senioritas mengakar dan bermekaran dalam pendidikan borjuis. Hanya dengan senioritas maka para pelajar dikorbankan di altar kapitalis. Pamflet Apa yang Diperjuangkan Sosialisme? (2013), menyinggung fenomena tersebut:
“Sistem pendidikan [borjuis] mengajarkan rakyat agar menaati wewenang dan tunduk pada aturan, dan media massa berusaha agar ajaran ini tidak dilupakan. Yang diajarkan di sekolah hanya supaya murid-murid menjadi buruh yang efisien, mengerti bagaimana menghitung dan membaca. Kesadaran tentang bagaimana masyarakat bergerak dianggap tidak dibutuhkan kecuali agar mengerti rantai komando. Sekolah “memperbaiki” rakyat agar sesuai dengan sistem. Maksusnya, kalau rakyat ikut sekolah yang “baik”, rakyat diajarkan bagaimana cara menyukseskan diri atau setidaknya diberi ilusi serupa. Tujuan sistem pendidkan [borjuis] lebih merupakan indoktrinasi daripada pendidikan, untuk menjamin nilai-nilai kapitalisme, persaingan dan kepatuhan menjadi kebiasaan.”
Itulah mengapa dalam masa-masa ospek mahasiswa angkatan baru tidak sedikitpun diperkenalkan dengan sosok mahasiswa pelawan, pembangkang dan pemberontak; melainkan mahasiswa-mahasiswa angkatan lama yang tampil mendukung tatanan. Spesies yang telah terdiferensiasi menjadi senior ini punya pandangan sesuai tatanan. Bagi mereka: dalam setiap pranata sosial ada aturan jenjang karir yang tersusun. Hanya untuk meniti karirnya diperlukan penyesuaian diri dengan kepentingan kekuasaan atau kelompok dominan. Begitulah komitmen, ketaatan dan kedisiplinan dipancangkan untuk melayani birokrasi-borjuasi. Melalui pelayanan inilah mereka meneguk hak istimewa bukan saja dipupuk sebagai senior, tapi juga mendapatkan imbalan-imbalan material lainnya: kemudahan, jaringan, bahkan pendanaan. Cita-cita umum mereka semuanya serupa: kuliah secepatnya, beroleh pekerjaan mudah dan hidup mapan dengan sanak-keluarga. Hampir tidak ada yang menyukai tantangan mematikan, petualangan membahayakan, apalagi menumpuh jalan penghancuran status-quo. Kampus menyukai dan mendukung keberadaan mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Lihat saja bagaimana panggung ospek disulap untuk memupuk citranya begitu rupa. Segala puja-puji di(re)produksi untuk menampilkan mereka sebagai prototip mahasiswa sempurna. Dalam kondisi inilah tanda yang merupakan hasil abstraksi pikiran manusia atas relasi-relasi sosial produksi (kebudayaan) direkayasa menjadi petanda ‘realitas’; yang membedakan pemakainya dengan kelompok lain, dan bisa juga dijadikan sebagai petanda yang dapat membuat konsumennya masuk dalam kelompok sosial tertentu. Jean Baudrillard (2001) menjelaskan itu semua:
“Jadi konsumsi merupakan proses klasifikasi dan diferensiasi sosial, artinya obyek atau tanda tertata sebagai suatu nilai yang menentukan status dalam hierarki sosial. Dengan demikian konsumsi menjadi bagian dari strategi yang menentukan bobot dalam distribusi nilai status. Konsumsi tidak bisa dilepaskan dari makna sosial lain seperti pengetahuan, kekuasaan, dan budaya. Ketiga hal ini sering dipakai untuk mengukur stratifikasi sosial. Proses diferensiasi sosial ini merupakan proses yang dihayati seakan sebagai kebebasan. Jadi perilaku itu memang seakan pilihan bebas [manipulasi kebebasan], seperti tidak ada perasaan dipaksa, juga bukan di bawah tekanan struktur tertentu.”
Arena konsumsi memang amat terstruktur. Jadi tidak mungkin panitia ospek mempunyai motivasi untuk memerintah dengan sendirinya, karena pasti ada kelompok yang menjadi patokan sikapnya: birokrasi kampus. Merekalah yang mengarahkan pandangan mahasiswa angkatan lama dan angkatan baru. Dalam keadaan inilah dominasi simbolis menampak sembunyi-sembunyi. Dominasi itu tidak disadari oleh korban dan pelakunya karena mengandaikan keterlibatan yang didominasi; bukan melalui kepatuhan pasif atau paksaan menerima suatu nilai, tapi karena bentuk persetujuan terhadap sudut pandang kelompok dominan. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai doxa: ‘sudut pandang penguasa atau dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal’. Itulah yang membuat banyak mahasiswa gampang terjerumus dalam rayuan citra yang dibangun birokrasi-borjuasi: kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan. Mereka tak sadar bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya lebih dahulu diberikan contohnya oleh kelompok dominan: elit-elit birokrasi pendidikan. Tetapi dengan berlangsungnya kegiatan ospek, maka bandulan relasi senior-junior dianggap sebagai kelumrahan. Inilah mengapa senioritas tidak menyeruap begitu saja, melainkan menjadi eksperesi paling nyata dari kepentingan kelas borjuis untuk mengontol dan mengawasi mahasiswanya. Terutama untuk melumpuhkan angkatan muda menjadi manusia-manusia pasif dan reseptif, tidak kritis apalagi menghendaki perubahan status-quo. Dalam keadaan inilah kaum muda ditipu-daya dan dibodohi begitu rupa. Begitulah apa yang mahasiswa angkatan baru dan angkatan lama maksud sebagai sebentuk ‘kebebasan’ memilih atau melakukan sesuatu; justru merupakan ajang ‘perbudakan’ terselubung. Dalam Manusia Satu Dimensi (2016), Herbert Marcuse menjelaskannya demikian:
“Kapitalisme, yang ditopang oleh teknologi, telah mengisi semua ruang-ruang sosial, politis, dan bahkan kesadaran kita. Kekuasaan totalitarian ini mempertahankan hegemoninya dengan merampas sikap kritis kita untuk berpikir negatif tentang sistem kapitalisme. Setelah itu dia memaksakan pula kebutuhan-kebutuhan palsu yang tidak kita perlukan, melalui iklan, kendali pasar, dan media massa. Dan apa yang dimaksud dengan kebebasan, tidak lain sebagai alat dominasi dan hegemoni.”
Dilaksanakan sebagai kewajaran maka senioritas yang berdiri di atas bangunan pendisiplinan, penaatan, pematuhan dan penundukan dapat mengancam perasaan, pikiran dan kehendak kemanusiaan. Senioritas yang dibiasakan soalnya mengambil bentuk ideologi yang mengacaukan kebebasan dan kesetaraan mahasiswa angkatan baru ketika berhubungan dengan mahasiswa angkatan lama. Dalam kondisi inilah relasi senior-junior yang telah bertransformasi menjadi seniorisme: menempatkan junior untuk terikat pada seniornya dengan buhul kesadaran palsu yang beragam—kesadaran yang menempatkan senior selalu benar, lebih tahu dan berpengalaman ketimbang dirinya; kesadaran membuat dirinya tak bisa belajar dan mencari pengalaman sendiri tanpa bantuan seniornya; kesadaran yang memosisikannya sebagai makhluk inferior dan seniornya menjadi superior; hingga kesadaran yang mengharuskan junior untuk melayani aneka kepentingan senior. Meski berkembang aneka kesadaran imajiner, tapi tampilan umum dari kesadaran itu adalah adanya perasaan keberutangan yang menjerat junior untuk membayarnya dengan cara memenuhi kepentingan senior. Dalam relasi seniorisme bentuk keberuntangan itu adalah munculnya rasa utang-budi dari junior yang merasa bahwa dirinya mendapatkan modal budaya (pengetahuan dan pengalaman) dari seniornya. Itu sebabnya junior yang memiliki kesadaran ini tidak bisa bersembunyi dari dorongan untuk membalas utangnya. Balasan yang diberikan ialah melalui penghormatan, penghargaan, bahkan pemujaan terhadap seniornya. Tenggelam pada kesadaran seperti inilah yang dalam praktiknya selalu menampakan wujudnya melalui ekspresi paling nyata dari relasi senior-junior: kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan junior kepada senior. Dengan sikap yang tersubordinasi itulah junior membalas utang-budi kepada seniornya. Namun semakin ia mengabdikan dirinya maka utangnya terhadap senior bukan malah dilunasi, melainkan tambah beronggok hingga dorongan melunasinya tak bisa berhenti begitu saja. Karena pada saat dia membalas jasa seniornya justru buhul pengikat direproduksi dengan dipertemukannya junior dengan pengetahuan juga pengalaman-pengalaman baru.
Hanya fenomena itu tak begitu menampak dalam ospek, tetapi dapat ditemukan dalam beragam kegiatan kaderisasi dan gerakan organisasi-organisasi mahasiswa tertentu. Lebih-lebih organisasi sektarian dan oportunis sebagai pelayan dan pendukung program-program kelas penguasa. Seniorisme memang menjadi tampilan umum dari organisasi yang tidak memiliki teori, program, tradisi dan metode yang tepat dalam melawan kapitalisme. Dalam organisasi mereka relasi patron-client berkembang sebagai penyangga akumulasi, hegemoni dan represi kapitalis dan negara borjuis. Pada masyarakat kapitalis, seniorisme menjadi salah satu bentuk ideologi mikro yang mengalir dari kran kapitalisme. Ideologi bagi Marx dan Engels merupakan produk aktivitas sadar manusia, tetapi keduanya mengusung ideologi untuk menunjukan kesadaran palsu yang bermekaran dalam masyarakat berkelas dengan pemisahan antara kerja-mental dan kerja-fisik (pembagian kerja). Begitulah Marx dan Engels mengkritik ilmu-pengetahuan borjuis yang menempatkan teori-teori ideologis untuk memproduksi kesadaran palsu: menempatkan pikiran, ide dan gagasan sebagai unsur-unsur pokok dan independen dari dunia nyata. Lewat Tentang Ideologi (2008), Louis Althusser mendedahkan kalau ideologi itu merupakan ‘representasi dari hubungan imajiner’ individu terhadap kondisi keberadaannya yang nyata. Ideologi bukan merupakan perwujudan kenyataan melainkan oranglah yang menghubungkannya dengan dunia nyata lewat persepsinya. Itulah mengapa ideologi diyakininya menyebar pada seluruh praktik kehidupan; tindakan kecil dan besar, pikiran awam dan ilmiah, maupun sela-sela terkecil kehidupan manusia. Dalam kondisi inilah setiap orang menginternalisasi ideologi ke dalam dirinya. Ideologi menjadi dasar tiap-tiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Persis demikianlah seniorisme tampil sebagai ideologi mikro dalam tatanan kapitalisme. Lahir dari kelas penguasa, maka seniorisme seiring-sejalan dengan kapitalisme. Mula-mula senior dijerat dengan suntikan pengetahuan dan pengalaman apa saja yang diberikan seniornya. Penyuntikan dilakukan melalui seabrek ajaran tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran, kesalahan, kebaikan, dan keburukan. Diiternalisasinya nilai-nilai itu oleh junior maka dia berarti berada di bawah kekuasaan seniornya. Hanya saja ia tidak sadar kalau dirinya telah dikuasai. Inilah mengapa dalam kubangan seniorisme, para junior tidak berani melanggar perintah dan keinginan orang-orang yang punya dominasi. Mereka begitu menyeringai, karena kebebasannya dibatasi. Tapi sekat keterbatasan dikaburkan seniorisme dengan taburan ilusi. Dalam Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (2015), Althusser menyebut fenomena tersebut sebagai interpelasi:
“Ideologi bertindak atau ‘berfungsi’ dengan satu cara yang ‘merekrut’ subjek-subjek di antara individu-individu, atau mengubah individu-individu menjadi subjek-subjek (ideologi) melalui operasi yang sangat presisi, yang saya namakan interpelasi atau memanggil … gerak-gerik subjek yang seolah-olah bebas ternyata dibatasi oleh relasi dalam struktur. Kebebasan subjek pada dasarnya adalah ilusi yang diciptakan ideologi agar ia merasa bertanggung jawab dan mendorong dirinya melakukan serangkaian tindakan menghidupkan struktur yang ada sebelum ia lahir … individu diinterpelasi sebagai suatu subjek (bebas) agar ia dapat taat sepenuhnya pada perintah-perintah Subjek [seniorisme-senioritas], agar dia membuat gerak-gerik atau tindak-tanduk dari ketaatan ‘sepenuhnya oleh dirinya sendiri’…. Dengan ketaatan yang diyakini sebagai kehendaknya, subjek menjalankan perannya seolah tanpa paksaan, seolah dengan kuasanya ia bekerja. Dengan begitu, tidak diperlukan pengawasan secara fisik, tidak perlu Subjek [seniorisme-senioritas] ada didekat subjek-subjek untuk memastikan mereka bekerja seperti yang diharapkan. Para subjek telah mengatur dirinya sendiri sebagai pihak-pihak yang taat dengan ilusi kebebasan dan otonominya.”
Apabila mahasiswa sudah diselimuti seniorisme dalam sebuah organisasi tertentu, maka sudah pasti dirinya akan menjadi pesakitan di hadapan kekuasaan seniornya. Kebergantungannya begitu rupa: ada junior yang tidak lagi memiliki rasa percaya diri untuk belajar secara otodidak, terdapat pula yang tak mampu bekehendak sendiri tanpa meminta nasehat seniornya, bahkan paling celaka muncul juga spesies yang menganggap sulit maju dan tumbuh jika enggan dididik dan dikembangkan seniornya. Fenomena ini menempatkan manusia terkungkung oleh otoritas di luar dirinya. Kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan dalam relasi seniorisme membuat perasaan, pikiran, dan kehendak manusia tidak berdaya. Mereka seolah kehilangan kehendak untuk menyangsikan apa-apa yang diinginkan senior. Inilah yang membentuk habituasi kader menjadi terbiasa menelan dogma, nenerima dikte, dan tunduk pada doktrin-doktrin vulgar. Keadaan begini justru menyulap junior serupa temuan teknologis canggih yang diprogram oleh seniornya. Terkadang dia punya keinginan untuk keluar dari kuasa namun tak mampu merealisasikannya. Karena kemerdekaannya hanya ada di pikiran sementara tidak dalam tindakan. Itu sebabnya seniorisme menjadi model didikan ala tuan dengan budak, yang meletakkan senior jadi gembala sedangkan junior menjadi dombanya. Modus pendidikan organisasi begini banyak sekali melahirkan sosok-sosok manusia robot sekaligus pandir. Jika tak percaya maka lihatlah bagiamana hubungan senior-junior di pelbagai organisasi-organisasi Cipayung Plus di sekelilingmu. Bukankah kaderisasi dan gerakan organisasinya kerap kali menampilkan fenomena pembodohan intelektual hingga robotisasi anggota begitu rupa?
Angkatan muda yang dibodohi dan menyerupai robot itu mudah sekali diperintah ke sana-ke mari untuk melakukan apa saja tanpa pamrih. Dirinya hanya bisa berkata: ‘siap senior’ atau ‘siap salah’. Kalau dulu ‘siap-siapan’ hanya ditemui di organisasi militer, maka kini yang demikian dapat ditemui di beragam organisasi mahasiswa yang menjadi pelayan dan pendukung kepentingan kelas penguasa. Dalam organisasi mereka berlangsung model pendidikan borjuis dengan bentuknya yang cenderung hierarkis. Makanya nyaris tidak mungkin junior meluruskan kesalahan apalagi membantah beragam omong kosong yang disemprotkan senior. Bahkan yang salah justru mudah sekali dipelintir jadi kebenaran oleh senior dengan segala prestise yang dimilikinya: lamanya berorganisasi, kebesaran jabatan, ukuran usia, keluasan jaringan, dan ketersediaan dana. Seniorisme tak mendorong kalian berpikir kritis dan menyangsi melainkan menjadi sesosok yang harus bertenggang rasa terhadap tipu-daya. Seniorisme menghadirkan ilusi mematikan: semua yang menjadi permintaan senior adalah bertujuan untuk mendidik juniornya. Makanya tatkala seorang junior merasakan ada ketidaklaziman dalam pengajaran yang dilakukan oleh senior; dirinya bukan malah melawan tapi justru kikuk. Dalam kondisi ini ia bahkan harus memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang sewalaupun dianggapnya sebagai tidak benar dan ngawur. Kala itu dia tidak memiliki kekuatan karena struktur dan relasinya memposisikannya begitu lemah. Sebagai junior dia mendapatkan dirinya dibuat menjadi penurut, pengekor, hingga agak tolol segala. Walau seabrek senior yang merawat seniorisme bukanlah berasal dari kelas borjuis, tapi praktik senioritas mengekspresikan kepentingan kapitalisme: mendisiplinkan, menundukan, dan menciptakan ketaatan buta pada norma-norma. Begitulah mereka menyangga status-quo. Doug Lorimer (2013) menjelaskannya:
“Dengan melihat status sosial mereka, para ideolog klas tertentu tidak harus berasal dari klas tersebut. Tetapi dengan mengekspresikan dalam bahasa ideologi kepentingan sebuah klas, mereka melayani kepentingannya dan mewakili agen-agen intelektualnya. Dalam kata-kata Lenin, “…para kaum terpelajar disebut begitu karena mereka yang paling sadar, paling tegas, dan paling tepat merefleksikan dan mengekspresikan perkembangan kepentingan klas dan pengelompokkan politik di masyarakat sebagai keseluruhan”…. Dalam masyarakat yang terbagi dalam klas, faktor yang menentukan seberapa banyak kebenaran yang ada dalam ideologi klas tertentu adalah peran sejarah yang dimainkan oleh klas tersebut dalam memuaskan kebutuhan vital masyarakat pada tingkat perkembangan yang ada…. Dalam periode kebangkitan borjuasi, jalan obyektif perkembangan ekonomi cukup direfleksikan pada ideologinya—filsafat, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Pada waktu yang sama ideologi tersebut berisi banyak ilusi-ilusi, sebut saja, gagasan bahwa sistem borjuis sementara secara sejarah adalah abadi dan sesuai dengan “hak alami” manusia, sifat dan akal mereka.”
Begitulah seniorisme melayani kepentingan kelas penguasa Jika pembaca adalah junior yang berasal dari organisasi-organisasi Cipayung Plus—organisasi sektarian dan oportunis yang melayani kepentingan kelas penguasa—bukankah sulit untuk menyangkal jalannya penindasan itu? Jika tidak percaya maka coba kalian tanyakan pada dirimu: sudah berapa kali melaksanakan keinginan senior yang menegorbankan kemampuan nalar, perasaan dan kehendakmu? Kenaifan demikian tumbuh karena hasrat manusia yang terdalam dibiarkan tersumbat oleh norma-norma yang berasal dari otoritas di luar dirinya (seniorisme). Pembatasan-pembatasan dari kelompok dominan tidak ditanggapi secara kritis. Tetapi cenderung dibiasakan dengan sikap dogmatis. Sikap ini sama sekali tak melatih untuk mempertanyakan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Makanya ketika seorang senior mengatakan bahwa survey, seminar, kuliah umum, atau demonstrasi itu benar; junior hanya bisa mengamininya lalu siap mengikutinya dengan cekatan. Junior-junior tidak pernah tahu atas kepentingan siapa kegiatan tersebut diadakan. Namun mereka biasanya cuma dicekoki sabda: ‘keterlibatan kalian merupakan bagian dari proses berorganisasi yang akan memberi banyak pengetahuan dan pengalaman’. Bahkan ketika dirinya tahu bahwa di balik agenda itu terselip kepentingan pragmatis-oportunis—baik untuk memperoleh jaringan, jabatan maupun uang oleh segelintir kalangan; tetapi lagi-lagi posisinya sebagai junior tak memberinya keberanian buat menentang tindakan pihak dominan yang penuh tipuan dan kelicikan. Kedudukannya yang inferior membuatnya mudah diperdaya lewat berbagai dalih yang melemahkan dan membingungkan. Dalih-dalih seniornya biasanya bersifat persuasif. Juniornya dibujuk dan dirayu untuk menjadi orang yang permisif. Bujukan dan rayuan dibingkai dalam kepraktisan. Fenomena inilah yang terjadi ketika junior diberitahukan: segala kegiatan yang diadakan itu akan memberikan manfaat kepada kalian; melatih jadi pencetus, mengajari membuat konsep dan menjalankan acara; membuka akses kepada para pemangku kepentingan publik; hingga memberi keuntungan materil. Dengan menghadapi godaaan besar maka junior tak segan-segan membebek: menjadi pendukung aktif atau panitia dalam segala hal yang dibenarkan para senior. Suasana pendidikan organisasi mahasiswa seperti ini amat dekaden, menanggalkan kemandirian, mematikan api perlawanan dan melanggengkan jalannya penindasan. Dalam Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis (2001), Erich Fromm menulis tentang ‘Mendidik si Automan’—bagian inilah yang melukiskan pendidikan borjuis itu begitu kelam:
“Mula-mula tiap pelajar menyimpan perasaan menentang dan berontak, tapi karena kedudukannya yang lemah biasanya seorang pelajar mesti mengalah. Maka jadilah proses belajar itu berujud penghapusan tanggapan antagonistik. Demi upaya penghapusan itulah maka proses belajar lalu menggunakan metode mengancam dan menghukum, menakut-nakuti sampai suatu cara yang lebih samar, yaitu lewat penyuapan atau penjelasan yang membingungkan. Penjelasan yang bisa membuat pelajar meninggalkan sikap menentang. Mula-mula ia berhenti untuk mengungkapkan setiap perasaan, lama-kelamaan ia berhenti untuk merasa.”
Dalam organisasi-organisasi Cipayung, keyakinan naïf dan pembodohan sistem kapitalisme dirawat melalui sebuah kelompok kepentingan. Untuk inilah setelah dikuasainya banyak junior maka mereka dimasukkan ke gerbong tertentu yang berada organisasi yang menjadi pelayan dan pendukung kekuasaan. Gerbong sebelumnya telah membesarkan seniornya hingga punya kemampuan menaklukan. Maka ditaklukannya junior-junior adalah berkat didikan senior-senior dalam gerbongnya juga. Gerbong soalnya tidak hanya memberi modal pengetahuan, melainkan pula sosial, ekonomi, dan terutama simbolik. Keempat modal itulah yang harus dipelihara dan diperbanyak melalui reproduksi aparat ideologis. Pengembangbiakan dilancarkan seorang senior dengan mendidik anggota-anggota organisasi menjadi makhluk yang berguna sebagai sekrup-sekrup penopang kekuasaannya. Merekalah yang dijadikan alat dalam mempertahankan, mengokohkan, dan menguatkan keberlangsungan kehidupan gerbong: hidup yang tak sekadar diselimuti kepentingan kelas borjuis tapi juga belenggu ketidakbebasan dan hierarki yang begitu rupa. Kala junior memasuki gerbong maka dia bukan cuma harus taat pada senior yang telah mendidiknya. Melainkan juga senior dari seniornya dan begitu seterusnya. Melalui gerbong mereka diajar serupa serdadu: punya garis komando. Kehidupan senior-junior di sebuah gerbong begitu sentralistik-birokratik: orang-orang yang berada di bawah berhubungan dengan yang di atasnya dengan sikap membeo tanpa sedikitpun memancang sikap kritis. Keadaan ini lagi-lagi dirawat sama seperti bagaimana awalnya juniornya berhadapan dengan seniornya: dilumpuhkan lewat suntikan seniorisme hingga diracuni kesadarannya. Selanjutnya untuk menguasai anggota organisasi tidak sekadar diluluhkan dalam jerat seniorisme melainkan pula gerbongisme. Gerbong tak hanya menebar ilusi pengetahuan dan pengalaman (budaya). Melainkan pula jaringan atau koneksi (sosial); uang, anggaran maupun pendanaan (ekonomi); dan pangkat, jabatan, serta kebesaran (simbolik). Seolah keempat kapital ini hanya bisa diperoleh lewat kekuatan dari gerbong. Berlandaskan keyakinan mistis akan kapital (modal, uang, dan sebagainya) inilah gerbongisme lahir sebagai ideologi yang lebih banyak mengandung kesadaran palsu.
Terselimuti dengan kesadaran palsu itulah maka junior diseret dalam kubangan ilusi yang meraksasa. Kemanusiaannya terancam oleh kepentingan apa saja. Soalnya seniorisme-gerbongisme lebih menekan individu. Makanya dalam membina dan mendidik juniornya mereka sering kali memerankan drama yang penuh kamuflase: dari kulitnya junior seperti dilatih menjadi seorang idealis, tetapi di bagian sel-sel dalamnya diajarkan jadi manusia yang begitu praktis, pragmatis, dan oportunis. Sebab kaderisasi dan gerakan dari organisasi yang melayani dan mendukung kekuasaan itu tak diinspirasi maupun dimotivasi kepentingan massa-rakyat-pekerja, melainkan menjadi pelayan kelas borjuis. Itulah mengapa junior-junior dibina dan dididik namun lewat kerja-kerja dangkal, tidak mencerahkan dan menggugahkan. Lihatlah bagaimana ada-ada saja yang melaksanakan kegiatan pesanan—seminar, kuliah umum, bahkan demo—guna memperoleh keuntungan pribadi atau gerbong. Banyak pula yang menjadi influencer, buzzer, tim survei pemilu, hingga panitia apa saja demi meraup imbalan. Beginilah gerbong-gerbong itu berpatron kepada para birokrat maupun politisi supaya menjadi besar dengan hubungan patron-client. Dari gerbong inilah kebanyakan muncul spesies-epesies korup dan haus kuasa: mereka biasanya berupaya merebut dan mempertahankan kekuasaan—baik di internal maupun eksternal organisasinya—dengan cara apapun, termasuk politik uang. Singkatnya, relasi-relasi seniorisme-gerbongisme semakin mereifikasi (membendakan) hubungan-hubungan sosial dalam organisasi. Senior-junior ditempatkan pada kondisi yang persis ditulis Marx—melalui ‘Manuskrip Ekonomi dan Filsafat’-nya—sebagai alienasi:
“Uang tampak sebagai kekuatan yang menganggu individu dan ikatan-ikatan sosial, yang mengklaim menjadi entitas yang mandiri. Uang mengubah kesetiaan menjadi pengkhianatan, cinta menjadi benci, benci menjadi cinta, kebenaran menjadi kesalahan, pembantu menjadi majikan, kebodohan menjadi kecerdasan, dan kecerdasan menjadi kebodohan … uang menukar setiap kualitas dan obyek dengan setiap yang lainnya, sekalipun kualitas itu saling bertentangan…. pertama, dalam proses kerjanya [aktivitas produktifnya—kuliah dan organisasi dengan segala kesibukannya yang tak membebaskan] manusia dipisahkan dari kekuasaan kreatifnya sendiri; dan kedua, objek-objek kerjanya [hasil kegiatan produktif: karya tulis, nilai, ijazah, dan beragam prestise berorganisasinya], menjadi makhluk-makhluk asing, dan akhirnya menguasainya, menjadi kekuatan yang independen dari pembuatnya.”
Ilusi dari seniorisme dan gerbongisme menghadang, mengendalikan, bahkan mematikan tindakan yang terbit dari pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Dalam kondisi inilah para korban seniorisme-gerbongisme persis mesin. Kemanusiaannya meluncur lantaran dipelintir kesadaran palsu dalam relasinya dengan kelompok dominan. Althusser menyatakan ideologi (borjuis) membawa manusia bergerak dalam relasi palsu namun seolah nyata. Tidak ada orang yang hidup tanpa ideologi karena manusia adalah ‘binatang ideologi’. Melaluinya maka semua agen produksi, eksploitasi dan represi, terus bergerak seirama dalam ketidaksadarannya untuk menjalankan (re)produksi. Keadaan seperti inilah yang terjadi pada tatanan masyarakat kapitalis: untuk memastikan dominasi kelas borjuis terhadap kelas pekerja, negara dan aparatusnya tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan praktis sekaligus sadis. Di ranah produksi, kapitalisme memproduksi ‘keterampilan’ yang nanti berguna untuk bekerja. Sedangkan dalam relasi produksi; kapitalisme memproduksi ketundukan pada aturan-aturan apa saja, terutama yang datang dari negara dan kapitalisme. Di kampus maupun organisasi mahasiswa pengabdi kekuasaan; kontrol dan pengawasan senior terhadap junior menjadi sistem yang sejalan dengan kepentingan kelas borjuasi. Itulah mengapa senioritas dan seniorisme mendekati junior serupa buruh saja: kerja-kerja yang diberikan kepada orang-orang yang diajarnya mengandung penindasan dan ekploitasi. Kita akan menemukan fenomena ini melalui analisis kelas Marxisme. Pemikiran Karl Marx tidak sama dengan Max Weber. Weber melihat dalam hubungan sosial masyarakat kapitalis ada kelompok yang mendapat sesuatu secara berlimpah dan ada pula yang dapatnya serba-kekurangan. Menurutnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat melandasi kehidupannya di atas persaingan yang lebih mirip permainan—sebab di dalamnya tidak ditemukan hubungan antagonistik. Sedangkan Marx memandangnya berbeda: tatanan kapitalis menempatkan kelas-kelas masyarakat melakukan persaingan tapi isinya adalah pertarungan yang tak terdamaikan dan menghancurkan (kontradiksi antagonis). Maka agendanya bukan hanya kompetisi mencari dan mengumpulkan kapital, tapi terutama penghisap dan kekerasan terhadap sesamanya. Inilah yang menjadi bahasan ‘filsafat kerja’ Marxisme: esensi kemanusiaan terkandung dalam kegiatan produksi—kerja. Proposisi demikian lahir melalui analisa pada hubungan sosial yang dilakukan lewat kerja. Friedrich Engels dalam Dialektika Alam (2005) bahkan berpendapat kalau kerja bukan sekadar sumber kekayaan, melainkan pula mampu mengembangkan dan membedakan kehidupan manusia dengan spesies lainnya:
“Semua kera antropoid [binatang yang menyerupai manusia, terutama dari bentuk fisiknya: orang-utan, simpanse, dan gorila] dapat berdiri tegak dan bergerak di atas kedua kaki mereka saja, namun hanya dalam suatu keadaan darurat dan secara sangat canggung. Sikap alamiah mereka adalah suatu sikap setengah tegak dan termasuk di situ penggunaan tangan mereka. Mayoritasnya menunjukan buku-buku kepalan tangan ke atas tanah dan, dengan kedua kaki mereka terangkat mengayunkan tubuh mereka melalui lengan-lengan mereka yang panjang, mirip sekali sebagaimana seorang pincang bergerak dengan bantuan penopang-penopang. Pada umumnya dewasa ini pun kita masih dapat menyaksikan di antara kera-kera semua tahapan peralihan dari berjalan di atas ke-empat anggota badan pada berjalan di atas kedua kaki. Tetapi tiada dari mereka yang menjadikan metode tersebut terakhir itu lebih dari pada suatu pengganti sementara … di kalangan kera sudah berlaku suatu pembagian tertentu dalam penggunaan tangan dan kaki. Yang pertama terutama digunakan untuk mengumpulkan dan memegang makanan, sebagaimana sudah terjadi/berlaku penggunaan cakar-depan di kalangan mamalia rendahan. Banyak kera menggunakan kedua tangan mereka untuk membangun sarang-sarang untuk diri mereka sendiri di pepohonan atau bahkan, seperti Orang-Utan, membangun atap-atap di antara cabang-cabang untuk perlindungan terhadap cuaca. Dengan kedua tangan mereka memegang anak-anaknya untuk melindungi diri terhadap musuh, atau memborbardir yang tersebut belakangan itu dengan buah-buah dan batu-batu. Dalam keadaan terperangkap dengan kedua tangan mereka, dilakukannya sebuah gerakan yang sederhana yang diturun (ditirukan) dari makhluk manusia. Tetapi justru di sinilah orang melihat betapa lebar jurang antara tangan yang tidak berkembang bahkan kera-kera yang paling antropoid dan tangan manusia yang telah sangat disempurnakan oleh kerja selama ratusan ribu tahun.”
Bagi Friedrich Engels, kerja merupakan aktivitas signifikan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Melalui kegiatan dan relasi produksinya maka manusia menemukan kemampuan mencipta ucapan artikulat dalam berhubungan dengan sesamanya. Kerja dan artikulasi kemudian menjadi dua rangsangan yang membuat sempurna perkembangan otaknya. Perubahan pada otak lalu bersamaan dengan berkembangnya organ-organ indrawinya. Puncak perkembangannya ini menjadi pembeda antara manusia dengan kera dan binatang-binatang lainnya. Maka melalui kerja-sama tangan, organ-organ bicara, dan otak; manusia dalam kehidupannya sebagai individu dan anggota masyarakat, berkemampuan melaksanakan operasi-operasi yang kompleks untuk menetapkan dan mencapai tujuan hidupnya. Sehingga dari generasi-ke-generasi kerja tadi makin berbeda, beraneka ragam, dan mengalami penyemurnaan-demi-penyempurnaan. Itulah yang berlangsung sepanjang sejarah kehidupan umat manusia: ketika agrikultur ditambahkan pada perburuan dan peternakan, setelahnya ditemukan cara menenun dan menganyam, hingga dilakukan pula pengerjaan logam dan tembikar, bahkan pernavigasian, dan simultan dengan majunya perdagangan dan industri maka lahirlah seni dan ilmu pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan persukuan—suku-suku manusia yang sudah mengalami pelbagai kemajuan akhirnya mengembangkan negara-negara dan bangsa-bangsa—di dalamnya tidak hanya terdapat sistem hukum dan politik, tapi juga bentuk-bentuk pikiran keagamaan. Hanya saja semua mode produksi (budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik) yang ada sekarang semuanya telah diarahkan semata-mata pada pencapaian efek kerja yang paling segera sekaligus berguna—praktis. Yakni, untuk memusatkan keuntungan ke tangan pemegang kekuasaan—kelas borjuis. Engels lewat karyanya menulis:
“Dalam hubungannya dengan alam, seperti dengan masyarakat, cara produksi sekarang terutama dan di atas segala-galanya hanya memikirkan hasil pertama, hasil yang paling dapat disentuh; dan kemudian dinyatakan keterkejutan bahwa akibat-akibat paling jauh dari tindakan-tindakan pada tujuan ini ternyata sangat berbeda sekali, bahkan teristimewa memiliki watak/sifat yang berlawanan … milik perorangan berdasarkan kerja individual mau tidak mau berkembang menjadi ketiadaan pemilikan apapun kaum pekerja, sedang semua keuntungan menjadi semakin dan kian terkonsentrasi di tangan kaum borjuis….”
Marx menyatakan kerja adalah syarat eksistensi manusia yang abadi dan alamiah. Hanya sistem kapitalis memerosotkan kerja-kerja manusia ke kubangan penyimpangan yang artfisial, dangkal, dan sangat pongah. Dalam produksi kapitalisme bangunan kerja bukan cuma menawarkan kompetisi biasa, tapi juga berisi aneka penindasa dan eksploitasi. Namun kekerasan dan penghisapan itu dimediasi oleh relasi sosial kelas pekerja dengan kelas borjuasi. Hubungan mereka terdiri dari empat tahapan: mulai dari relasi properti, relasi pembagian kerja, relasi pembagian surplus, hingga relasi produksi. Mula-mula (1) keadaan manusia dalam ‘relasi properti’: hak milik menentukan siapa sebagai tuan dan siapakah yang menjadi hamba. Melaluinya maka penguasa dapat memperlakukan yang dikuasainya secara suka-suka. Sebab, kepemilikian pribadi melegitimasi perbuatan arbitrer pemilik alat produksi. Selanjutnya (2) ‘relasi pembagian kerja’ ditentukan dari kepemilikan properti barusan: ada yang memerintah dan terdapat pula yang diperintah. Maka hubungan manusia dengan sesamanya mematutkan perbudakan. Dengan menjadi budak seseorang dipaksa untuk melayani majikan. Itulah mengapa setelahnyanya (3) pada ‘relasi pembagian surplus’ terjadi bagi hasil namun tidak proporsional: keuntungan lebih banyak diberikan kepada pemegang hak milik pribadi ketimbang makhluk yang diperintah dan diperasnya. Soalnya pekerja-upahan (perbudak modern) bukan hanya tidak memiliki properti, tapi terutama tak berkuasa atas dirinya. Inilah yang membuat budak-upahan bekerja sekadar buat bertahan hidup saja. Hingga dalam (4) ‘relasi produksi’: proletariat mendapat balasan atas kerjanya tapi tak lebih untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sementara tuan dapat memilih apa yang ingin dilakukannya terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja budak-budaknya—entah menggunakannya untuk konsumsi, atau mengakumulasinya. Hanya untuk melancarkan kepentingan akumulasi dilaksanakanlah reproduksi: mengulang keempat relasi eksploitasi tadi tanpa henti-hentinya, sekaligus menentukan—supra-struktur ideologi, hukum, pendidikan, budaya, moral, agama, bahkan negara—sebagai penyangga kegiatan produksinya di basis-struktur (produksi).
Metode yang dipakai Marx untuk menganalisa hubungan sosial dalam kerja itu adalah holisme (pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta, baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental-psikis, dan kebahasaan, serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang integral). Dengannya ia melihat eksploitasi yang lahir dalam relasi sosial antara pekerja dengan majikannya. Kaum Marxis menyebut penindasan tersebut sebagai ‘pengambilalihan nilai-lebih’. Nilai-lebih lahir melalui proses penciptaan komoditas oleh para buruh lewat waktu kerjanya. Dalam waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan (re)produksi buruh juga menghasilkan nilai-tukar yang abstrak: kemampuan kerja. Meski abstrak namun kemampuan kerja itu berguna untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan—nilai lebih—bagi siapa-siapa yang memperkerjakannya. Hanya saja nilai-lebih tidak berasal dari pertukaran, tapi melalui pembelian tenaga-kerja dan penggunaannya di dalam produksi. Dalam Marxisme untuk Pemula (2006), Rupert Woodfin dan Oscar Zarate menjelaskan bahwa keuntungan pihak penindas itu didapat dengan cara mengeksploitasi kerja-kerja manusia:
“Keuntungan mestinya dihasilkan dari modal variabel [pembelian tenaga-kerja], di sinilah keniscayaan eksploitasi kapitalisme terjadi. Kaum buruh diwajibkan untuk bekerja lebih lama daripada rata-rata. Kaum buruh diwajibkan untuk bekerja lebih lama dari pada rata-rata nilai-tukar yang sesungguhnya dalam kerja mereka…. Modal variabel, atau sejumlah uang yang dihabiskan untuk tenaga kerja, menambahkan nilai tukar komoditi karena, selama proses produksi kaum buruh menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk bekerja yang tidak menghasilkan apapun bagi mereka sendiri. Buruh memberikan nilai lebih banyak pada komoditas daripada yang dibayarkan untuk mereka. Mereka dieksploitasi.”
Dalam kampus dan organisasi-organisasi Cipayung Plus pembelian tenaga-kerja itu dilakukan kelompok dominan melalui penyaluran pengetahuan dan pengalaman kepada siapa-siapa yang dididiknya. Makanya relasi perbudakan modern dari senior-junior menampakkan fenomena bacin: kebebasan junior dapat disubtitusi (ditukar/diupah/dibeli) menggunakan aneka modal—budaya, ekonomi, sosial, maupun simbolik. Bahkan melalui pendidikan borjuis inilah banyak junior yang dikorbankan untuk membentuk kharisma senior. Mereka harus tahu kalau kerja-kerja untuk melayani seniornya, gerbongnya, atau aktivitas-aktivitas berorganisasinya dengan relasi senior-junior telah lama memupuk kualitas ketokohan senior yang pandai memanfaatkannya. Begitulah kharisma seabrek tokoh Cipayung Plus dan pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa internal kampus dibangun melalui hubungannya dengan massa: memberi perintah, didengarkan ceramahnya, diikuti atau dikawal langkahnya, dan sebagainya. Jadi, tidak tepat jika memakai teorinya Weber tentang kharisma: ‘mengacu pada suatu kualitas tertentu dari kepribadian individual dengan kekuatan mana dia dianggap luar-biasa dan diperlukan sebagai seseorang yang mendapat kekuasaan/kekuatan atau kualitas adi-kodrati, adi-insani, atau sekurang-kurangnya secara khusus tak ada taranya’. Kharisma macam ini amat mistis dan berdiri di atas idealisme. Sementara kharisma dalam kenyataannya begitu nyata: berasal dari relasi-relasi sosial dalam kerja-kerja manusia. Tengoklah terbentuknya kharisma tokoh di mana-mana: berlangsung melalui fethisisme komoditas—citra-citra ketokohan direifikasi berdasakan kepemilikan atas aneka kapital: modal budaya (pengetahuan dan pengalaman), simbolik (jabatan, gelar, maupun pangkat), sosial (koneksi politik, jejaring dagang, garis keturunan), maupun ekonomi (uang, anggaran, kemampuan produksi dan konsumsi). Hanya setiap kapital ini berasal dari kerja manusia—memerlukan tenaga produkif dan relasi produksi—untuk menghasilkan aneka kapital. Dalam menciptakan kapital, kerja dalam masyarakat kapitalis bersifat sosial: meniscayakan pengerjaan kolektif dan hasilnya dikonsumsi massal—begitupun dalam organisasi mahasiswa internal kampus dan Cipayung Plus.
Pada analisis terakhir itulah kerja atau aktivitas manusia secara massallah yang membentuk kharisma. Singkatnya: khariswa tidak terberi, tapi melewati pelbagai diferensiasi: merupakan sesuatu yang historis dan terikat pada masa dan tempat sehingga dapat dilatih, direncanakan ataupun diperhitungkan melalui kerja manusia yang bersifar sosial, massal—kerja-massa. Secara sederhana: lihatlah dalam beragam organisasi! Perbandingkanlah antara organisasi yang mempunyai banyak anggota dengan yang sedikit jumlah keanggotaan: tentu yang lebih mudah membentuk kharisma kepemimpinan pengurus atau ketua umumnya—adalah organisasi yang memiliki onggokan anggota. Tetapi keberadaan banyak anggota tidak akan menjamin pembentukan kharisma ketokohan seorang pemimpin apabila anggota-anggotanya tidak bekerjasama; minimal segan dan menggugui aneka arahan dari pengurus atau ketua umumnya. Dengan kata lain: kharisma seseorang dibentuk oleh kerja-massa yang mengikuti, menuruti, atau diatur, dikontrol dan diawasi oleh pengurus maupun ketua umumnya. Atau dalam pernyataaan yang sesederhana dan sesingkat mungkin: kharisma dibentuk oleh massa yang menciptakan panggung untuk pemimpinnya. Begitulah senior-senior di organisasi-organisasi internal kampus dan Cipayung Plus beroleh kharismanya: dibangun di atas kerja-kerja juniornya. Sekarang apabila junior tidak mampu memasang sikap kritis terhadap apa saja yang diperintahkan seniornya maka ini menjadi penanda: dirinya sudah terjerambab dalam kesadaran palsu dalam hubungannya dengan seniornya. Kala itu relasi properti berlangsung begitu rupa. Di situ ada pihak yang mempunyai hak milik pribadi atas kapital apa saja. Modal inilah yang dikomodifikasi agar menghasilkan keuntungan, terutama yang berguna mendominasi pihak yang menjadi sasarannya. Karena kepemilikan modal sedari awal memberi legitimasi (hak istimewa) kepada pemiliknya untuk berkuasa. Makanya seorang senior yang bermodal (berprestise) beroleh kuasa atas junior yang tidak memiliki modal sepertinya.
Itulah yang berlangsung saat junior di-ospek di kampus maupun dikader dalam organisasi Cipayung Plus: hubungannya dengan siapa-siapa yang mendidiknya bagaikan tuan dengan hamba. Konsekuensi dari kepemilikan terhadap modal tertentu menentukan relasi pembagian kerja di antara mereka. Pembagiannya menempatkan senior sebagai orang yang berhak memberi perintah, sekaligus memposisikan junior menjadi seseorang yang berkewajiban menerima dan melaksanakan permintaan seniornya. Hubungan keduanya persis yang terjadi dalam suasana perburuhan: menampilkan parodi perbudakan manusia oleh sesamanya. Tetapi pertama-tama juniornya tidak diupah dengan uang, melainkan kapital budaya; isinya seabrek nilai-nilai, terutama moralitas yang mengekang. Setelah nilai tersebut berhasil diinternalisasi, maka junior kemudian dibawa masuk ke suasana grup pergaulan tertentu dalam hierarki senior-junior di kampus-kampus atau hierarki gerbong pada kehidupan organisasi-organisasi Cipayung Plus. Hanya di pergaulan atau gerbong inilah junior bakal bertemu dengan banyak sekali senior pula. Lebih khusus pada sebuah gerbong: junior pasti akan menemukan seabrek senior yang punya pengetahuan dan pengalaman, jaringan, anggaran, jabatan, kuasa, dan sebagainya. Dirawatnya relasi senior-junior dalam kampus dan organisasi itu berdiri di atas kepentingan kelompok dominan. Melalui beragam aturan dan hierarki maka junior-junior itu disulap menjadi pasakitan. Angkatan muda bukan hanya diajari untuk mengejar prestise, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi tentara cadangan industri atau aparat-aparat pelayan kekuasaan. Inilah mengapa di balik bangunan lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi Cipayung Plus itulah kaum muda tak dididik untuk bebas, setara, dan bersolidaritas; melainkan diajari dengan aneka pengejaran kepentingan pragmatis-oportunis.
Berdiri untuk mempertahankan status-quo maka institusi-institusi ideologis itu mengajarkan manusia-manusia yang dididiknya untuk bersaing antar-satu sama lainnya hingga menundukan sesamanya. Memang budaya senioritas yang dimulai sejak ospek di kampus-kampus maupun yang dibangun dalam pelbagai organisasi pelayan kekuasaan memiliki motif serupa: berdiri di atas persaingan untuk mengejar keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Diajarkan berlomba-lomba meraih untung apa saja maka banyak junior yang ditenggelamkan dalam situasi perbudakan modern: teralienasi dari kebutuhan, aktivitas, bahkan kehidupan dengan manusia lainnya. Dalam keadaan inilah posisinya sangat inferior dan sukar melakukan perlawanan kepada gerombolan yang mendominasinya. Daripada menentang, kalian justru semakin diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai yang disuntikan kelompok dominan dalam relasi senior-junior: kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. Bahkan semakin diinternalisasinya citra-citra atau kesadaran palsu suntikan kelas penguasa itulah yang membuat junior bukan hanya mengabaikan ketertindasannya, tapi juga cenderung menganggap perlawanan, pembangkangan, atau pemberontakan sebagai sesuatu yang irasional akan sistem dan struktur yang berlaku. Junior-junior akhirnya tenggelam dalam kebudayaan yang membujuk dan merayu untuk terus-menerus meniru apa-apa yang berguna dalam melanggengkan status-quo. Hubungan senior-junior sewaktu ospek dan beragam ajaran di organisasi yang melayani kepentingan kelas borjuis memperlihatkan itu semua: senioritas tampil sebagai kebudayaan bahkan bertransformasi menjadi ideologi yang menuntut junior tak sebatas meyakini ajaran seniornya, namun pula meniru apa saja yang ditampilkan senior maupun gerbongnya. Pada Dilema Manusia Rasional (1982), Hokheimer menjelaskan peniruan itu sebagai bentuk mimesis dari manusia-manusia primitif di masa lalu yang terulang kembali tapi di tingkatan lebih tinggi:
“Meski mimesis sudah disingkirkan oleh sikap rasional, tapi mimesis itu ternyata muncul kembali justru lewat sikap rasionalnya tadi. Pada zaman ini orang modern mengira dengan sadar, ternyata tidak sadar: bahwa kesadaran untuk mengadaptasikan diri kepada lingkungannya sama saja dengan kealamiahan untuk meniru lingkungannya seperti dilakukan oleh anak-anak atau masyarakat-masyarakat primitif. Alasannya, orang modern tidak lagi kritis terhadap segala kaidah, kategori atau tuntutan yang dipasang masyarakat. Ia malah menyebut rasional kalau orang mau menerima realitas dan menyesuaikan diri kepadanya. Maka ia meniru begitu saja semua kaidah, kategori, atau tuntutan masyarakat, tanpa mempersoalkan lagi dengan sadar apakah semua itu masih patut dianggap rasional. Sikap demikian itu sebenarnya meniru secara alamiah, bukan menerima dengan kesadaran yang kritis. Di sinilah mimesis ini adalah tanda kemenangan alam [dan masyarakat kapitalis] yang bisa dan berhasil ‘mengalamiahkan’ dan ‘mengirasionalkan’ manusia justru lewat sikap rasionalnya.”
Melalui budaya senioritas maupun ideologi seniorisme-gerbongisme maka pikiran, perasaan, dan kehendak manusia dikurung dalam penjara identitasnya sebagai junior. Sementara dengan mempertahankan relasi senior-junior; kelas penguasa terus-menerus mengontrol dan mengawasi banyak kaum muda yang tersebar di pelbagai kampus dan organisasi yang melayani kepentingannya. Di bawah pendidikan borjuis kepentingan itulah yang berusaha dilancarkan dengan menuntut junior untuk meyakini, mengonsumsi dan meniru apa saja yang menjadi ajaran, citra, kelakuan senior dan birokrasi kampusnya. Akibatnya bukan hanya kesadaran korban yang dimanipulasi, tapi juga daya hidupnya didisiplinkan hingga ditundukan begitu rupa. Bangunan kesadaran palsu yang didiktekan oleh kelompok dominan bahkan dengan serampangan menghambat perkembangan ilmu-pengetahuan dengan menentukan bacaan dan gagasan apa yang patut dikonsumsi. Kemudian bukan hanya asupan keilmuan yang ingin mereka kendalikan, tapi terbanter adalah penilaian baik, buruk, benar, dan salah. Inilah yang membuat junior terancam dalam tipu-daya pendidikan borjuis. Doxa kekuasaan telah membuat pandangan kader terus membebek pada mereka yang melayani kepentingan kelas borjuis dan menyangga tatanan masyarakat kapitalis. Itu sebabnya kebebasan berpikir dikikis aneka kepongahan. Makanya gagasan-gagasan berbeda gampang sekali dihinakan. Keadaan inilah yang mengakibatkan kebebasan tidak mampu disalurkan ke bentuk tindakan, melainkan diikat basi dalam pikiran.
Itulah mengapa junior tak berdaya berhadap-hadapan dengan orang-orang dari kelompok dominan. Dirinya bukan saja merasa tertekan untuk mendeklarasikan pandangan tapi juga ketakutan dalam mencetuskan tindakan. Jadilah ia mahluk yang tak punya pendirian dan begitu mudah diarahkan, bahkan dikendalikan oleh mereka yang menggunakan pengetahuan dan kekuasaan untuk mendakukan kebenaran. Begitulah strategi yang digunakan kelompok dominan untuk membungkam dan memaksakan kehendaknya kepada para korban. Kala itu junior-junior mendapati dirinya sangat malang: seperti spesies yang tidak sanggup menyangsikan keinginan dan perintah. Keadaan ini jika terus dibiarkan maka akan membuat kaum muda terus-menerus membebek karena tidak punya kemandirian dan inisiatif. Untuk itulah keberanian harus dimiliki untuk melawan dominasi. Keberanian mesti disulut dari benturan yang terjadi akibat perlakuan arbitrer kelompok dominan. Inilah yang akan mempertajam kontradiksi internal dalam diri seseorang. Tekanan-tekanan yang sudah enggan lagi untuk ditampung akan melecut sikap berani dalam mempercepat perubahan. Pada saat itulah manusia memeluk teguh kebebasannya untuk mengembangkan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dengan begitu citra, pandangan, dan peniruan yang ditampilakan senior mampu ditentang. Penolakan terhadap perlakuan kelompok dominan mengharuskan junior melakukan perlawanan melalui pengaktifan pikiran kritis. Dalam Wacana Kuasa/Pengetahuan (2013), Michel Foucault menyebutnya sebagai kemampuan menjawab tantangan untuk mengurai atau menganalisa hubungan kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran:
“Dengan membongkar hubungan kekuasaan yang disembunyikan akan mendorong tumbuhnya perlawanan agar semakin memperluas lingkup kebebasan. Lalu lingkup baru ini memungkinkan suara yang tercekik dan terpinggirkan bisa mengungkap. Dalam konteks inilah, kebebasan kita ditantang untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam bertindak. Orang tidak lagi terkungkung oleh tradisi, norma atau aturan yang cenderung mengekang perubahan. Hanya dalam suasana kebebasan di mana beragam bentuk dominasi dibongkar sehingga dimungkinkan menghasilkan pengetahuan yang dapat melawan cara memerintah yang dominan, bahkan bila pengetahuan itu memakai selubung kebaikan dan nilai-nilai luhur.”
Albert Einstein pernah berkata: ‘keyakinan tanpa akal sehat terhadap otoritas adalah musuh kebenaran yang paling buruk’. Dia lalu menganjurkan untuk menjadi manusia merdeka karena kebebasan adalah dasar penting untuk lahirnya semua nilai yang baik. Perjuangan merebut kebebasan akan membawa kita pada kesetaraan. Hanya perjuangan ini membutuhkan sikap berani melawan, membankang, atau memberontak pada tatanan. Sikap ini bukan kurang ajar, melainkan bentuk penghormatan terhadap kebenaran dan kemanusiaan. Pemikiran itu diyakini Alexander Berkman sebagai gagasan alternatif untuk memekarkan kebebasan: ‘kita harus belajar untuk menghormati kemanusiaan sesama kita, bukan untuk menyerang atau memaksanya, bersumpah untuk menghentikan paksaan dalam bentuk apapun: memahami obat bagi kejahatan terhadap kebebasan adalah memiliki lebih banyak kebebasan, bahwa kebebasan adalah ibu dari keteraturan’. Hanya kebebasan dalam masyarakat kapitalis adalah semu dan ilusif. Begitulah bukan kebebasan yang maha-penting di tengah hegemoni kapitalis tapi kesadaran yang mendorong untuk berlawan dan menjadi bagian dari perubahan. Prasyarat untuk beroleh kesadaran macam ini bukanlah keberanian semata, tapi lebih-lebih pengorganisasian diri dalam organisasi revolusioner. Sebuah organisasi yang membawa tugas historis untuk menggulingkan kapitalisme dan membangun dunia baru: masyarakat tanpa kelas—tanpa penindasan dan penghisapan manusia dan alam oleh minoritas pemilik alat produksi.
Hanya dengan tingkat kesadaran yang tinggi–yang didapat dari aktivitas-aktivitas politik bersama organisasi revolusionerlah–kebebasan dapat direbut dari cengkeraman kelompok dominan. Dengan membangun atau bergabung dalam organisasi revolusioner maka junior tidak hanya membebaskan dirinya tapi juga berjuang melawan penindasan demi memperjuangkan pembebasan bagi seluruh massa-rakyat—kaum tertindas, terhisap dan miskin. Kini kesadaran harus dibangkitkan lewat pengorganisiran diri. Inilah sikap berlawan paling realistis yang bisa junior lakukan. Sekarang sudah waktunya perlawanan diarahkan terhadap doxa, konsumerisme, dan mimesis yang dianjurkan kelompok dominan. Ketiganya amat kejam bagi perkembangan pikiran, perasaan dan kehendak-kehendak kemanusiaan. Sebab dominasi terhadap pandangan, citra, dan kebiasaan itu akan mengekang kehidupan dalam sebuah cetakan seragam: menjadi pelayan kepentingan kekuasaan dan penyangga masyarakat kapitalis. Tidak adanya perlawanan sama halnya dengan membiarkan berdirinya monemun kehidupan senior-junior yang diprogram secara mekanik oleh kelas borjuis. Sekaranglah waktunya pembangkangan dikobarkan. Tidak jenuhkah kalian meminum pandangan, memuja citra, dan meniru kelompok dominan? Sampai kapan kebenaran diproduksi lewat otoritas para bajingan? Telah berapa lama akal sehat, nurani, dan keinginanmu ditanggalkan? Apa yang membuat kalian begitu nyaman menjadi korban pembodohan dan meluncur ke kubangan kehinaan? Sudah tidak adakah nyalimu untuk meneguhkan kebebasan dan kesetaraan dengan manusia lainnya? Tak beranikah kau menggugat kenapa mereka terus merayumu dengan kebenaran instan? Sebagai pemikir progresif, Amr Ibn Bahr punya kesimpulan tersendiri tentang kebenaran; baginya pergulatan untuk mencapai kebenaran tak bisa dikawal dengan model berfikir yang kolot, naïf, dan kaku. Itulah kenapa kebenaran tidak boleh dipaksakan atau disuntikan seperti model pendidikan borjuis, manipulasi tanda, dan peniruan. Sebab, kebenaran merupakan bagian seni penalaran dan harus dicari melalui perjuangan:
“Dalam setiap manifestasi kehidupan, baik dalam kehidupan binatang atau tumbuhan, saya menjumpai pelajaran, dan saya benci, teramat membenci, intelek-satu-dimensi. Saya hidup memerangi moral picik kaum perompak akal, kaum tradisionalis, dan kaum birokrat. Saya hidup membela keindahan pemikiran dan seni bernalar. Sebab tidak hanya nalar yang dibenci oleh kaum perompak melainkan juga estetika nalar.”